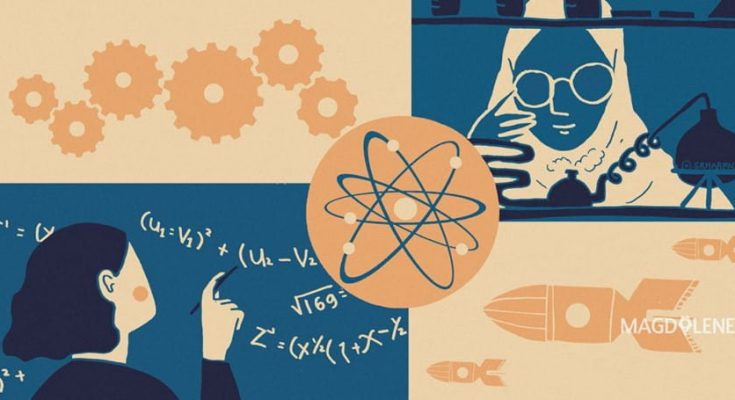10 Nama Pahlawan Perempuan Indonesia yang Harus Kalian Ketahui
Ada banyak sekali nama pahlawan perempuan Indonesia yang telah berjasa memperjuangkan nasib negara ini. Tapi, yang jauh lebih banyak diperkenalkan, baik di instansi pendidikan (sekolah), dan instansi-instansi lainnya adalah pahalawan Indonesia yang berjenis kelamin laki-laki. Sedikitnya yang diperkenalkan, pasti lagi-lagi R. A. Kartini, Nyi Ageng Serang, Dewi Sartika, dan Rasuna Said. Padahal, kalau dicermati lewat beragam literatur yang ada, ada banyak sekali nama pahlawan perempuan Indonesia yang belum kita ketahui dan jarang diperkenalkan.
Baca Juga: Kepemimpinan Perempuan Islam Indonesia yang Membumi
Pahlawan nasional perempuan Indonesia itu tidak terbatas pada pahlawan yang berjuang memerdekakan Indonesia dari penjajah ratusan tahun silam, tapi juga pahlawan yang berjasa di masa modern seperti sekarang ini. Perjuangan para pahlawan perempuan ini juga beragam, dimulai dari perjuangan fisik di medan perang, sampai perjuangan ideologi di bidang pendidikan, diplomasi, pengembangan komunitas, dan lain-lain. Tanpa jasa mereka, tentu saja kemerdekaan yang dicapai tidak akan seluas sekarang.
Berikut ini adalah daftar nama pahlawan perempuan Indonesia yang perlu kamu ketahui:
1. Pahlawan Perempuan Indonesia yang Terlupakan: Martha Christina Tiahahu

kemudian ada Martha Christina Tiahahu, pejuang perempuan yang berasal Desa Abubu, Pulau Nusa Laut yang lahir pada tanggal 4 Januari 1800.
Waktu itu, saat baru menginjak umur 17 tahun, seorang Martha sudah percaya diri untuk mengangkat senjata untuk melawan para penjajah. Martha juga diketahui tidak pernah bolos dalam memberikan energi buat kaum perempuan untuk mendukung laki-laki saat di medan peperangan.
Dibalik perlawanannya selama masih remaja, Martha harus menetap dengan sang ayah yaitu Kapitan Paulus Tiahahu yang diberikan hukuman mati oleh tetara Belanda. Martha pun mulai terganggu kesehatan fisiknya serta mental, dan akhirnya Martha pun ditangkp bersama rekannya yang ada 39 orang. Lalu digiring ke Pulau Jawa dengan kapal Eversten untuk dijadikan pekerja paksa di kebun kopi.
Keadaan fisik Martha yang terus memburuk di dalam kapal. Kejadian ini diketahui karena ia tidak mau makan atau di beri obat. Sampai akhirnya pada tanggal 2 Januari 1818, Martha pun meninggal dan dikuburkan dengan diberikan penghormatan secara militer ke Laut Banda.
2. Laksamana Malahayati

Satu lagi nama pahlawan perempuan Indonesia asal Aceh, Keumalahayati. Malahayati termasuk perempuan kelahiran Aceh Besar pada tahun 1550. Dengan kegagahannya serta keberaniannya, Malahayati menjadi pemimpin buat dua ribu orang tentara Inong Balee atau para janda pahlawan yang sudah meninggal akibat perang.
Dengan ketabahan hatinya, pahlawan perempuan ini bersama pasukannya bertempur melawan kapal serta benteng pertahanan Belanda sekaligus berhasil membunuh Cornelis de Houtman yang terjadi pada tahun 1599 tepatnya tanggal 11 September. Karena keberaniannya tersebut, akhirnya Malahayati mendapatkan sebuah gelar Laksamana.
Akan tetapi, pada tahun 1615 Malahayati harus meninggal ketika sedang dalam sebuah misi yang harus melindungi Teluk Krueng Raya dari gempuran tetara Portugis yang dikepalai oleh Laksamana Alfonso De Castro.
3. Nama Pahlawan Perempuan Indonesia Berasal dari Jawa Tengah: Nyi Ageng Serang

Pahlawan perempuan yang berasal dari keturunan Sunan Kalijaga yaitu R. A. Kustiyah Wulaningsih Retno Edi, atau biasa diketahui dengan nama Nyi Ageng Serang.
Perempuan yang lahir di tahun 1752 ini merupakan putri dari Natapraja yang merupakan seorang Pangeran dan ikut berperang melawan para penjajah bersama anggota keluarganya seperti kakak dan ayahnya. Seiring dengan keluarganya, ia terus bersemangat saat membela rakyat apa lagi waktu kematian kakaknya karena melindungi Pangeran Mangkubumi waktu berperang dengan Paku Buwono I yang didukung Belanda.
Baca Juga: 4 Pahlawan Perempuan dari Jawa Barat adalah Tokoh Feminisme
Meskipun sang ayah, kakak, serta sang suami akhirnya meninggal lebih dulu dalam perlawanannya, Nyi Ageng Serang dengan gagah tetap memimpin para pasukan yang masih ada pada usia 73 tahun.
Kegagahan serta kehebatan Nyi Ageng Serang juga mendapat pembenaran dari Pangeran Diponegoro karena sukses membuat strategi sampai dipercaya menjadi salah satu penasehatnya. Akan tetapi, sebelum perang Dipenoegoro usai, Nyi Ageng Serang harus menghembuskan napas terakhirnya diumur 76 tahun karena pandemi penyakit malaria yang diidapnya.
4. Nama Pahlawan Perempuan Indonesia dari Jawa Barat: Maria Walanda Maramis

Jika Kartini serta Dewi Sartika merupakan pahlawan perempuan dari Jawa Barat, ada pula pahlawan emansipasi perempuan dari Minahasa yaitu Maria Walanda Maramis. Perempuan yang lahir pada tanggal 1 Desember 1872 ini juga berjuang dalam membebaskan perempuan dari kurangnya pendidikan.
Setelah pernah bersekolah di Melayu di Maumbi, lebih tepatnya di wilayah Minahasa Utara, selama 3 tahun dan tidak bisa meneruskan bangku pendidikan ke level yang lebih lagi, Maria akhirnya memutuskan untuk membikin semacam lembaga yang kasih nama yaitu Percintaan Ibu Kepada Anak Temurunnya atau kalau di singkat menjadi PIKAT, dengan tujuan untuk mengembangkan pendidikan buat para kaum perempuan.
Lewat PIKAT, perempuan pribumi mendapatkan dasar dari berbagai ilmu buat berumah tangga misalnya masak, menjahit, mengasuh bayi, dan yang lain. semasa ia hidup, Maria sibuk bekerja di PIKAT sampai akhirnya ia meninggal pada tanggal 22 April 1924.
5. Pahlawan Nasional Perempuan Berhijab: Rasuna Said

Perempuan yang lahir di Jakarta bernama lengkap Hajjah Rangkayo Rasuna Said atau lebih populer dengan panggilan Rasuna Said juga merupakan seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk persamaan hak perempuan dengan laki-laki.
Menurut Rasuna Said, kaum perempuan tidak cuma didapat dari hasil mendirikan sekolah, tetapi juga dapat berjuang ke dalam politik. Rasuna Said pun terus bekerja serta berjuang dengan membuat pidato politik saat membela negara.
Akan tetapi saat pidatonya yang melawan pemerintah Belanda, dia dikenakan Speek Delict Law, yaitu peraturan atau hukum yang berasal dari Belanda buat orang yang berpidato atau berbicara memusuhi Belanda. Rasuna Said akhirnya dibekuk bersama dengan temannya, Rasimah Ismail, lalu di jatuhi hukuman penjara di daerah semarang pada tahun 1932.
Indonesia akhirnya bisa merebut kemerdekaan pada tahun 1945, Rasuna Said langsung aktif menjadi Dewan Perwakilan Sumatra untuk menjadi wakil rakyat Sumatra Barat dan pernah dijadikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat atau DPR RIS.
Rasuna Said juga pernah menjabat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung sampai akhirnya ia meninggal pada tanggal 2 November 1965 karena ia mengidap penyakit kanker darah.
6. Nama Pahlawan Perempuan Indonesia Berasal dari Sulawesi: Andi Depu

Terakhir yang kita bahas adalah Andi Depu, merupakan seorang perempuan yang punya nama lengkap Andi Depu Maraddia Balanipa yang juga seorang pahlawan perempuan berasal dari Tinambung, Sulawesi Barat.
Karena keberanian serta kekuatannya, seorang Andi Depu sukses mempertahankan daerahnya dari gempuran Belanda. Tidak sampai situ saja, Andi Depu juga dengan gagah berhasil menaikan bendera Merah Putih waktu tentara Jepang menyerbu Mandar waktu tahun 1942.
Baca Juga: Tokoh Perempuan Disney Masih Terjebak Stereotip Negatif Perempuan Pemimpin
Kegigihan seorang Andi Depu yang bisa kita jadikan contoh ini kemudian diberikan sebuah tanda Bintang Mahaputra Tingkat 4 dari Pak Soekarno langsung. Dan juga, Pak Jokowi juga memberikan sebuah gelar Pahlawan Nasional buatnya serta 5 tokoh bangsa yang lain tertuang pada dektrit Presiden Republik Indonesia Nomor 123 pada tahun 2018 mengenai pemberian Gelar Pahlawan Nasional.
7. Opu Daeng Risaju

Opu Daeng Risaju merupakan salah satu anggota Partai Sarekat Islam yang sangat berberpengaruh, khususnya di Sulawesi Selatan. Dia menjadi anggota PSII cabang Pare-Pare, lalu mendirikan dan memimpin PSII cabang Palopo pada tahun 1930. Dia aktif menjadi seorang perempuan yang melawan penjajahan dengan cara modern, yaitu dengan gencar memperkenalkan ide tentang kemerdekaan bangsa Indonesia ke kerabat dan tetangga-tetangganya.
Ketidak sukaan Belanda pada upaya Opu Daeng Risaju ini membuat dirinya ditangkap selama 12 bulan dengan tuduhan bahwa ia telah menghasut rakyat. Pada tahun 1933, ia kembali ditangkap karena gerakan-gerakannya dianggap semakin membahayakan. Ia divonis kerja paksa selama 14 bulan. Tak berhenti sampai di situ, perjuangan Opu Daeng Risaju masih berlanjut sampai masa penjajahan Jepang, di mana ia mempengaruhi pembentukan cabang PSII di berbagai wilayah lain.
8. Sri Mangunsarkoro

Sri Mangunsarkoro merupakan ketua pertama dari organisasi Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari). Sri Mangusarkoro berhasil menjadikan Perwari sebagai organisasi yang vokal memperjuangkan hak-hak perempuan dalam pernikahan dengan pendekatan liberal-feminis.
Perwari memfokuskan perjuangan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang mengatur keadilan bagi perempuan di dalam pernikahan, seperti mendorong adanya ketentuan monogami, usia minimal pernikahan, kesetaraan ketentuan dalam perceraian, hak milik dan warisan, serta hak dan kewajiban suami dan istri dalam pernikahan. Di bawah pimpinan Sri Mangunsarkoro juga Perwari gencar melakukan forum publik, mengadakan petisi, demonstrasi di jalanan, dan delegasi dengan pemerintah untuk melancarkan agenda mereka.
Baca Juga: Perempuan Pemimpin dalam Film: Kurang Representasi, Diseksualisasi
Sebelum menjadi ketua Perwari, Sri Mangunsarkoro sudah aktif menginisiasi dan mengetuai berbagao gerakan dan organisasi perempuan. Seperti memimpin Kelompok Pekerjaan Tangan Keputrian Jong Java cabang Salatiga, ketua Keputrian Jong Java pada 1920, ketua Wanita Taman Siswa cabang Jakarta, Ketua Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta pada tahun 1935, sampai ketua Badan Penyelidikan Perburuhan Perempuan Indonesia (BPPPI).
9. Soewarni Pringgodigdo

Soewarni Pringgodigdo merupakan pendiri organisasi perempuan sekuler yang progresif bernama Isteri Sedar. Soewarni berhasil membawa Isteri Sedar menjadi organisasi perempuan yang secara eksplisit menunjukkan ideologi organisasinya yang feminis-demokratis.
Lewat majalah terbitan organisasi itu yang bernama Sedar, Soewarni gencar menyampaikan kritik dan perlawanannya terhadap ketidak setaraan gender, poligami, pentingnya kesetaraan peran dalam pernikahan, serta keadilan bagi perempuan di ranah publik dan domestik. Soewarni yang sangat membenci poligami sempat mendapat penilaian buruk dari berbagai golongan, sampai dicibir karena dianggap terlalu galak. Tapi ia tetap konsisten memperjuangkan ideologinya tersebut melalui berbagai medium.
10. Maria Ulfah Santoso

Lahir di Serang, Banten, pada 18 Agustus 1911, Maria Ulfah Santoso adalah perempuan pertama dari Hindia Belanda yang lulus dari sekolah hukum di Belanda. Begitu pulang ke Indonesia, ia pun aktif membela hak-hak perempuan, terutama dalam hal pernikahan di mana mereka mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari laki-laki yang menjadi suami mereka.
Setelah Indonesia merdeka pada Desember 1945, Maria menjadi salah satu inisiator Kongres Perempuan Indonesia di Klaten, Jawa Tengah dan menjadi ketua untuk badan yang membahas perumusan Undang-Undang Perkawinan.
Nah, kita sudah membahas nama Pahlawan perempuan Indonesia yang sudah punya jasa besar serta keberaniannya bisa kita jadikan contoh serta pembelajaran buat anak muda. Semoga generasi sekarang bisa mempunya jiwa seperti para pahlawan Indonesia ya.
Read More