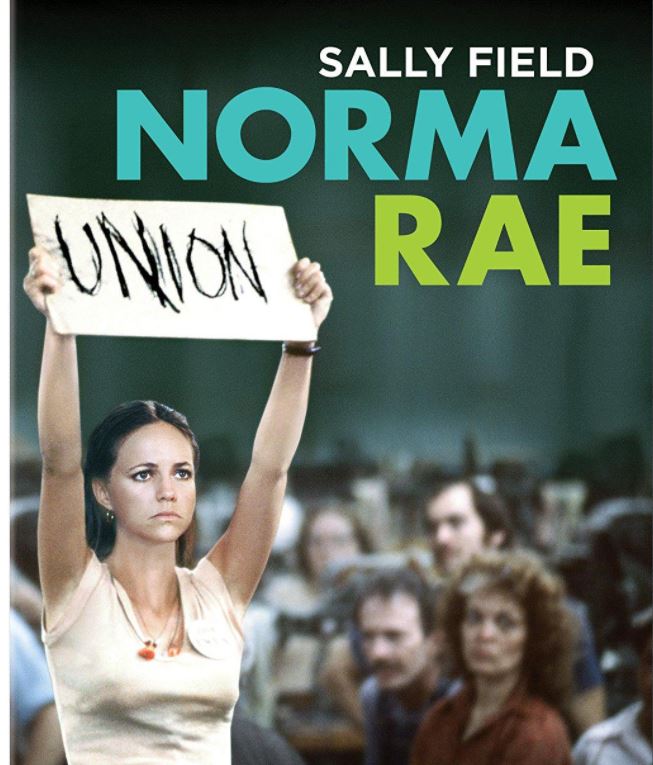Pada Senin (1/2) lalu, perempuan pemimpin nasional Myanmar peraih Hadiah Nobel Perdamaian 1991, Aung San Suu Kyi, serta Presiden U Win Myint ditangkap seiring kudeta pemerintahan oleh pihak militer.
Ini bukanlah kali pertama Suu Kyi dan presiden kesepuluh Myanmar itu ditangkap. Sejak 1989 hingga 2010, Suu Kyi sempat berkali-kali dijadikan tahanan rumah, sementara Win Myint telah beberapa kali dipenjara saat militer memerintah, salah satunya akibat protes terhadap penguasa yang ia lakukan pada 1988.
Meskipun National League for Democracy (NLD)—partai yang dipimpin Suu Kyi dan tempat Win Myint tergabung–berhasil menang telak pada pemilihan umum November lalu, militer Myanmar membuat narasi bahwa kemenangan tersebut adalah hasil penipuan. Dilansir BBC, ketegangan antara militer dan pemerintah telah lama berlangsung dan semakin menjadi seiring kekalahan partai yang digawangi militer, Union Solidarity and Development Party (USDP) di parlemen.
Akhirnya pada awal Februari ini, militer mengambil alih listrik di bawah komando Jenderal Ming Aung Hlaing, yang kini menjadi pemimpin Myanmar. Jalan menuju ibu kota, Naypidaw, dan Yangoon diblokade. Siaran dari saluran televisi lokal dan internasional diputus, sementara koneksi internet dan telepon juga dikendalikan militer. Bank pun dipaksa menghentikan kegiatannya. Seiring dengan kudeta ini, 24 menteri dan deputi dicopot dari jabatannya serta jam malam diberlakukan mulai dari pukul 20.00 hingga 6.00.
Demokrasi Myanmar kembali di bawah ancaman karena keadaan ini. Sejumlah pemimpin negara lain mengecam kudeta militer di sana. Banyak warga Myanmar marah mendapati keadaan negara mereka tetapi sejauh ini, belum ada protes terlihat sebagaimana pada dekade-dekade lalu. Sebagian dari mereka takut berurusan dengan militer, terlihat dari orang-orang yang enggan menyebutkan nama mereka saat memberi testimoni pada BBC.
Awal Mula Perjuangan Aung San Suu Kyi Meraih Demokrasi
Seperti sejumlah perempuan pemimpin di Asia, termasuk Indira Gandhi, Benazir Bhutto, dan Megawati Soekarnoputri, Suu Kyi adalah putri pemimpin negara. Perempuan kelahiran 19 Juni 1945 ini merupakan putri dari Jenderal Aung San, pejuang kemerdekaan yang secara de facto menjadi pemimpinBurma (nama negara sebelum menjadi Myanmar). Aung San mati dibunuh pada tahun 1947 bersama enam orang lainnya dalam rapat dewan eksekutif (pemerintah bayangan yang dibentuk Inggris sebelum transfer kekuasaan) sekitar enam bulan sebelum Burma merdeka.
Baca juga: Perempuan Pembela HAM Mangsa Empuk Kekerasan
Sejak tahun 1960, Suu Kyi tinggal di India seiring penunjukan ibunya sebagai duta besar Myanmar di sana. Pada 1964, Suu Kyi melanjutkan studi di Inggris bidang Filsafat, Ekonomi, dan Politik di St. Hugh’s College of Oxford Academy, lalu meraih gelar PhD dari School of Oriental and African Studies, University of London pada 1985. Saat di Inggrislah ia bertemu dengan Michael Aris, akademisi Inggris yang kemudian menjadi suaminya.
Ia sempat hendak melanjutkan studi di New York, AS, pada 1969, tetapi menundanya karena memilih bekerja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pada 1988, Suu Kyi pulang ke Myanmar karena ibunya jatuh sakit, sementara suami dan anak-anaknya tetap tinggal di Inggris. Kala itu, militer sudah berkuasa sejak tahun 1962. Pada tahun kepulangan Suu Kyi, terjadi pembunuhan massal terhadap warga yang memprotes pemerintahan militer di bawah U Ne Win seiring munculnya krisis ekonomi dan politik. Hal itulah yang mendorong Suu Kyi untuk bangkit bersuara dan memperjuangkan demokrasi serta hak asasi manusia di sana dengan jalan nonkekerasan.
Aung San Suu Kyi Menjadi Tahanan Rumah dan Terancam
Pada 1989, Suu Kyi bersama beberapa orang lainnya yang juga pro-demokrasi mendirikan NLD dan menjabat sebagai sekretaris jenderal. Partai tersebut menjalin kerja sama dengan beberapa partai politik berbasis etnis seperti Shan Nationalities League for Democracy (SNLD) dan Arakan League for Democracy (ALD) untuk membangun rekonsiliasi nasional.
Pada 20 Juli 1989, Suu Kyi dijadikan tahanan rumah di Rangoon (sekarang Yangoon) tanpa diadili. Pemerintah militer sempat menawarkan kebebasan untuknya asalkan ia hengkang dari Myanmar, tetapi Suu Kyi menolak sampai militer mau membebaskan tahanan politik dan mengembalikan kekuasaan pada pemerintahan sipil.
Tahun berikutnya, NLD memenangi Pemilu dan meraih lebih dari 80 persen kursi parlemen, tetapi pemerintahan militer tidak mau mengakui hal tersebut dan lanjut menguasai negara sampai tahun 2011. Berita mengenai Hadiah Nobel Perdamaian kepada Suu Kyi pada 1991 semakin membuatnya ditekan oleh pemerintah militer.
Pada 1995, Suu Kyi sempat dibebaskan. NLD kembali menunjuknya sebagai sekretaris jenderal partai tersebut, mengabaikan larangan dari pemerintah untuk mengganti siapa pun di posisi kepemimpinan partai. Pada tahun inilah Suu Kyi terakhir kali melihat suaminya karena setelah itu, izin berkunjung ke Myanmar yang Aris ajukan berkali-kali ditolak pemerintah. Tahun 1999, Aris meninggal di Inggris karena kanker dan tanpa kehadiran Suu Kyi yang masih berada dalam situasi pelik.
Baca juga: Alami Intimidasi dan Kekerasan, Perempuan Pembela HAM Harus Dilindungi
Suu Kyi terus aktif menyuarakan demokrasi walaupun aktivitasnya sangat dibatasi pemerintah sejak 1997. Pada 2000 sampai 2002, Suu Kyi kembali menjadi tahanan rumah karena melanggar larangan militer baginya untuk meninggalkan Rangoon. Setelah dibebaskan, Suu Kyi memang bisa bepergian ke beberapa kota, tetapi tetap diawasi pemerintah.
Serangan dari pihak pro-pemerintah kepadanya kembali muncul pada 2003 ketika NLD berkonvoi di Depayin. Dalam kerusuhan antara pihak NLD dan pendukung pemerintah, sejumlah orang tewas. Karena kejadian itu, Suu Kyi ditahan di penjara Insein, Rangoon, kemudian lagi-lagi menjadi tahanan rumah. Awalnya, masa tahanan Suu Kyi berlangsung sampai 2007, tetapi militer memperpanjangnya berkali-kali sampai akhirnya ia dibebaskan pada November 2010.
Tahun 2009, seorang laki-laki Amerika bernama John Yettaw sempat nekat berenang sejauh 2 kilometer menyeberangi Danau Inya menuju rumah Suu Kyi untuk bertemu dengannya. Kendati Suu Kyi tidak mau menemuinya dan meminta dia untuk pergi, Yettaw memohon untuk tinggal sejenak karena kelelahan.
Akibat kejadian ini, hukuman untuk Suu Kyi diperpanjang. Sejumlah upaya di pengadilan untuk mengadvokasi Suu Kyi dilakukan, tetapi pemerintah tetap bersikukuh menghukumnya. Suu Kyi bahkan sempat dijatuhi vonis penjara tiga tahun karena insiden Yettaw, tetapi hukuman tersebut diganti menjadi 18 bulan tahanan rumah.
Suu Kyi Tak Bisa Jadi Presiden
Tahun 2012, pada pemilu sela, yang khusus diadakan di antara pemilu reguler saat ada jabatan politik yang kosong, Suu Kyi dan NLD meraih 43 kursi dari total 45 kursi di parlemen, membuatnya menjadi pemimpin pihak oposisi. Kemenangan pun kembali diraihnya atas partai militer pada 2015, tetapi ia tidak bisa menjadi pemimpin negara karena
memiliki anak-anak berkebangsaan Inggris. Meski demikian, Suu Kyi tetap dipandang sebagai pemimpin Myanmar secara de facto.
Di tengah kepemimpinan presiden yang sekarang menjabat (sampai sebelum kudeta), Suu Kyi berperan sebagai penasihat negara (state counselor). Posisi ini disahkan secara hukum oleh presiden kesembilan Myanmar, Htin Kyaw pada 2016.
Posisi yang diduduki Suu Kyi ini dianggap setara dengan posisi perdana menteri dan berpotensi lebih kuat dibanding posisi presiden. Sementara mayoritas warga menyambut baik peran Suu Kyi tersebut, pihak militer menolak mengakui undang-undang yang melegalisasi posisi penasihat negara.
Baca juga: Meneladani Kepemimpinan Jacinda Ardern di Tengah Pandemi
Aung San Suu Kyi Dikecam Masyarakat Global Karena Masalah Rohingya
Selain Hadiah Nobel Perdamaian, Suu Kyi juga sempat menerima gelar kehormatan Freedom of the City of Oxford pada 1997, diikuti dengan gelar yang sama dari beberapa kota lainnya di Inggris Raya, karena ia dianggap berjasa menentang penindasan militer di negaranya.
Suu Kyi juga menerima honorary degree dari banyak universitas di berbagai negara, serta gelar warga negara kehormatan dari pemerintah Kanada pada 2007. Tahun 2009, Amnesty International memberikan penghargaan tertinggi Ambassador of Conscience Award kepadanya.
Sejak 2017, situasi berubah 180 derajat. Konflik etnoreligius terjadi di negara bagian Rakhine dan menyebabkan tewasnya banyak warga Rohingya, kelompok Muslim minoritas di Myanmar. Seiring dengan itu, ratusan ribu warga Rohingya dipaksa meninggalkan Rakhine dalam operasi militer dan mayoritas hidup terkatung-katung sebagai pengungsi di beberapa negara.
Pihak militer memegang peran besar dalam pembersihan etnis Rohingya dan Suu Kyi dianggap menutup mata terhadap kejadian tersebut. Kegagalan Suu Kyi dalam menghentikan pembunuhan massal, pemerkosaan, dan banyak pelanggaran hak asasi manusia terhadap Rohingya pada akhirnya mendorong berbagai pihak untuk menarik simpati terhadap Suu Kyi, bahkan mencopot penghargaan-penghargaan yang pernah diterimanya.
Dalam kurun 2017-2018, Suu Kyi telah kehilangan gelar Freedom of the city dari sejumlah kota, Elie Wiesel Award dari United States Holocaust Memorial Museum, Honorary Presidency dari London School of Economics, serta UNISON honorary membership (serikat perdagangan). Pemerintah Kanada juga mencabut gelar warga negara kehormatannya pada 2018. Pada tahun yang sama, Amnesty International pun mencopot gelar yang pernah mereka berikan pada Suu Kyi.
Nama Suu Kyi, yang sempat dijadikan titel junior common room di St. Hugh, University of Oxford, dicabut, begitu juga dengan lukisan wajahnya yang dipajang di sana. Ratusan ribu orang telah menandatangani petisi untuk meminta Yayasan Nobel untuk mencabut Hadiah Nobel Perdamaian yang dimiliki Suu Kyi, tetapi permintaan tersebut ditolak.
Penangkapan Suu Kyi saat ini membelah opini publik menjadi dua. Sebagian menyayangkan hal tersebut terjadi karena itu menandakan cederanya demokrasi yang sudah susah payah dibangun di sana. Namun, sebagian lainnya tidak merasa bersimpati, bahkan malah merayakan penangkapan Suu Kyi tersebut, seperti yang dilakukan pengungsi Rohingya di Bangladesh.
Foto diambil dari Post-Conflict Research Center.
Read More