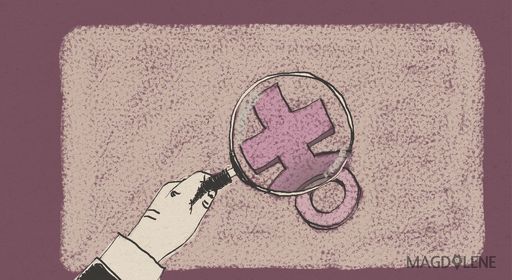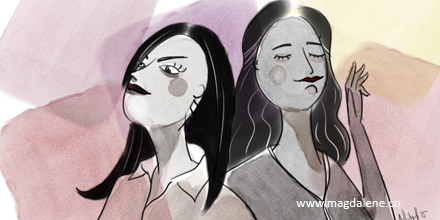
Tantangan Perempuan dalam Sektor Bisnis dan Pemerintahan
Kendati dalam masyarakat Indonesia perempuan kerap dianggap sebagai pencari nafkah tambahan setelah laki-laki, sebagian dari mereka menunjukkan dirinya berdaya untuk menjadi setara atau bahkan memiliki pendapatan lebih tinggi lewat bisnisnya. Tidak sekadar untuk mencari uang, perempuan-perempuan yang terjun dalam dunia ekonomi dan bisnis juga memulai usaha untuk mewujudkan aktualisasi diri dan meningkatkan kemandirian finansialnya.
Imbas positif dari terjunnya perempuan dalam dunia ekonomi dan bisnis tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri. Orang-orang di sekitarnya mulai dari keluarga juga merasakan hasil pekerjaan mereka.
Menurut Nadia Sarah, pebisnis dan salah satu founder komunitas bisnis perempuan SheStarts.id, perempuan yang pandai berbisnis bisa menjadi panutan bagi anak-anaknya.
“Kalau dalam satu keluarga ibunya pandai berbisnis atau memiliki kemampuan, artinya ibunya punya suara dalam keluarga. Ini merupakan pendidikan buat anaknya bahwa perempuan juga sosok yang tangguh, punya posisi di rumah,” kata Nadia.
“Enggak usahlah sampai jadi CEO di bisnis besar, yang penting bisa menghasilkan uang sendiri, mandiri, dan percaya diri. Bisa ambil keputusan juga. Ini yang nanti akan ditularkan perempuan ke anak-anaknya,” tambah perempuan yang memiliki bisnis di bidang konsultasi manajemen dan sumber daya serta konsultasi pendidikan ini.
Selain itu, kiprah perempuan di sektor ekonomi dan bisnis berpengaruh pula pada negara.
“Partisipasi perempuan dalam ekonomi dapat memacu produktivitas dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kita harus terus mendukung partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi, salah satunya melalui kebijakan industri rumahan,” ujar Pribudiarta Nur Sitepu, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam acara The International South Pacific, Indonesia Enterpreneurship Camp pada Maret 2019.
Potensi dan Tantangan Perempuan dalam Berbisnis
Di sektor ekonomi, peran penting perempuan terlihat mulai dari level industri rumahan atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memang banyak dijalankan oleh perempuan. Dalam laporan berjudul “Women-owned SMEs in Indonesia: A Golden Opportunity for Local Financial Institutions” yang dibuat International Finance Corporation (2016), dikatakan bahwa di Indonesia, 51 persen usaha kecil dan 34 persen usaha menengah dimiliki oleh perempuan. Kelompok gender tersebut berkontribusi sebesar 9,1 persen dari total produk domestik bruto (GDP) negara ini.
Potensi perempuan dalam menyokong ekonomi tidak lepas dari karakteristik mereka. Menurut Sarah Diana Oktavia, pendiri usaha Roti Eneng, perempuan memiliki benefit berupa rasa empati yang tinggi dalam dirinya yang berpengaruh besar terhadap keberlangsungan bisnis.
Baca juga: Pelajaran Soal Kepemimpinan Perempuan dari Drakor ‘Start-Up’
“Itu modal yang oke banget untuk mencari insight dari pasar yang akan kita masuki. Waktu merintis usaha ini di awal, aku ngobrol sama banyak orang untuk tahu produk apa yang harus aku hasilkan nanti,” kata Diana dalam webinar bertajuk “Geliat Ekonomi UMKM Perempuan di Tengah Pandemi” (2/12), yang diselenggarakan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
Potensi lain yang perempuan miliki adalah hadirnya inkubasi bisnis dan komunitas-komunitas yang menambah jejaring perempuan dalam menjalankan UMKM. Lewat mentoring dan proses belajar dan berjejaring yang dilakukan dalam komunitas, perempuan bisa meningkatkan kapasitasnya untuk mengembangkan bisnis.
“Di awal saya bangun usaha dengan teman-teman. Brainstorming dengan sesama pendiri dan belajar sama senior kuliah, silaturahmi ke mantan bos saya. Dalam bisnis kalau enggak ada networking, it will be painful,” kata Nadia.
Terkait mentoring, sebagian perempuan yang punya privilese lebih bisa menyewa jasa konsultan atau mentor. Tetapi bagi yang tidak punya, networking kembali lagi menjadi hal efektif untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas diri dalam bisnis, ujar Nadia. Banyaknya akses informasi terkait bisnis di dunia digital maupun lewat kenalan-kenalan di komunitas merupakan potensi yang perlu digali di tengah keterbatasan privilese tadi.
Dalam SheStarts.id, Nadia dan rekannya menekankan relasi sisterhood dalam memberi dukungan bagi sesama pebisnis perempuan. Tidak hanya menjadi wadah untuk berbagi cerita bisnis masing-masing, SheStarts.id juga dibuat sebagai wadah perempuan untuk berkonsultasi dengan sejumlah pengusaha dan banyak pihak lain yang membantu mereka mengembangkan bisnisnya.
“Kita perlu belajar dari siapa saja, bukan hanya dari yang berhasil, tetapi dari yang tidak berhasil juga,” imbuh Nadia.
Dalam menjalankan bisnis, lebih banyak tantangan yang mesti perempuan hadapi dibanding laki-laki. Salah satunya adalah pandangan negatif orang sekitarnya dan minimnya dukungan keluarga saat perempuan memutuskan membuka bisnis. Misalnya, anggapan perempuan tidak seharusnya berpendapatan lebih tinggi dari laki-laki, atau tidak lebih sibuk di urusan pekerjaan dan sebaiknya mengurus anak-anak saja.
“Tantangan memulai bisnis bagi perempuan paling banyak datang dari keluarga karena ada tuntutan peran ganda perempuan. Karena hal itu, sering kali perempuan kebingungan dalam hal time management antara bisnis dan keluarganya,” kata Nadia.
Peran laki-laki menjadi penting dalam mendukung perempuan di dunia ekonomi dan bisnis. Pribudiarta menyatakan, jika perempuan masuk ke ruang bisnis dan tidak didukung oleh laki-laki yang menjadi partnernya, besar kemungkinan usahanya akan mengalami kegagalan.
“Partisipasi laki-laki untuk perempuan telah menjadi suatu hal yang wajib, agar kesetaraan gender dapat terwujud dalam berbagai bidang,” kata Pribudiarta.
Sementara itu, menurut Staf Khusus Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tb. Fiki Satari dalam webinar serupa dengan yang dihadiri Diana, pandemi membawa kesulitan tersendiri bagi perempuan pelaku UMKM. Di antaranya adalah turunnya permintaan, berkurangnya likuiditas (kemampuan untuk membayar utang yang harus segera dibayar), minimnya kapasitas dan fasilitas digital, serta kurangnya sumber daya.
Masalah Keberanian dan Rasa Sungkan yang Besar
Tantangan lain kerap dihadapi perempuan saat mengembangkan bisnisnya dapat bersumber dari individu. Misalnya dalam hal meminjam modal, Nadia menilai bahwa hal ini dipengaruhi juga oleh keberanian perempuan dalam mengambil risiko.
“Dari segi kesempatan untuk mendapat modal dari perbankan, laki-laki dan perempuan sebenarnya sama. Kreditur atau investor membukanya sama. Tetapi, perempuan jarang yang risk taker, dia terlalu berhitung. Ah sudahlah, segini saja cukup,” jelas Nadia.
Padahal, kata Nadia, ada penelitian yang mengatakan bahwa kredit yang diberikan pada perempuan itu yang lebih lancar dibanding laki-laki. Dari segi risiko yang akan diambil pemberi kredit, risiko memberi kredit kepada perempuan sebenarnya cenderung lebih kecil.
“Perempuan di awal lebih tekun dalam memulai bisnis. Tapi masalahnya, ketika scale up usahanya, dia perlu modal, waktu dan pegawai lebih banyak, mereka cenderung berpikir lebih panjang. Laki-laki cenderung memulai usaha dengan skala dan risiko lebih besar dari awal,” ujar Nadia.
Selain itu, sikap sungkan yang banyak sebagian perempuan pebisnis berpengaruh juga terhadap UMKM-nya. Misalnya, saat ia berelasi bisnis dengan keluarga atau teman-temannya.
“Rasa enggak enakannya perempuan harus dikurangi. Ia harus berani bilang tidak, berani mengatakan pemikirannya. Pada saat kita belajar menerima penolakan waktu mencoba menawarkan bisnis kita, kita juga belajar menolak,” tutur Nadia.
Tokoh-Tokoh Perempuan Sukses di Bidang Ekonomi dan Bisnis
Meski ada banyak tantangan bagi perempuan di dunia ekonomi dan bisnis, sebagian dari mereka berhasil mematahkan tantangan tersebut dan melesat dalam kariernya. Bahkan, kapasitas mereka sampai diakui oleh dunia internasional.
Beberapa nama pebisnis perempuan Indonesia yang disebutkan dalam Forbes 30 Under 30. Ada Fransiska Hadwidjana dengan bisnis aplikasi jual-beli barang bekasnya, Prelo, dan Laboratorium AugMi. Menyusul Eugenie Agus yang bersama kakaknya menjalankan bisnis puding Puyo dan telah memiliki 40 gerai di seluruh Indonesia. Lalu, ada Talita Setyadi dengan bisnis makanannya yang bernama Beau dan produknya telah masuk ke 100 kafe di Indonesia.
Baca juga: Pelajaran Penting tentang Jadi Perempuan Berdaya dari Martha Tilaar
Di level pemerintahan, ada Sri Mulyani Indrawati yang punya rekam jejak kesuksesan yang panjang dalam menduduki posisi-posisi strategis, baik di pemerintahan maupun lembaga dunia.
Selain menjabat sebagai Menteri Keuangan pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, Sri Mulyani juga pernah menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia. Belum lama ini, Sri Mulyani juga dinyatakan sebagai Menteri dengan kinerja terbaik pada masa pandemi oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia.
Namanya kerap tercatat dalam daftar perempuan berpengaruh dunia versi Forbes. Media lain seperti Finance Asia, majalah keuangan dari Hong Kong pun menobatkannya sebagai Menteri Keuangan Terbaik di Asia Pasifik. Sejumlah penghargaan dari tataran internasional pun diraihnya seperti Statepersons Awards dari Asian Business Leadership Forum tahun 2019 dan Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) dalam World Government Summit 2018.
Tahun ini, ekonom Mari Elka Pangestu menambah daftar perempuan Indonesia di bidang ekonomi yang menduduki jabatan di Bank Dunia. Sejak Maret 2020, ia bertugas sebagai Direktur Pelaksana, Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan di sana.
Seperti halnya Sri Mulyani, Mari juga pernah menjabat di pemerintahan yakni sebagai Menteri Perdagangan tahun 2004-2011, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2011-2014. Dirinya juga tercatat sebagai penasihat Komisi Global Geopolitik Transformasi Energi Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) di Abu Dhabi.
Mari juga berkiprah dalam bidang pendidikan sebagai profesor ekonomi internasional di Universitas Indonesia, serta menjadi asisten profesor di Sekolah Kebijakan Publik Lee Kuan Yew dan Sekolah Kebijakan Publik Crawford, Universitas Nasional Australia.
Read More