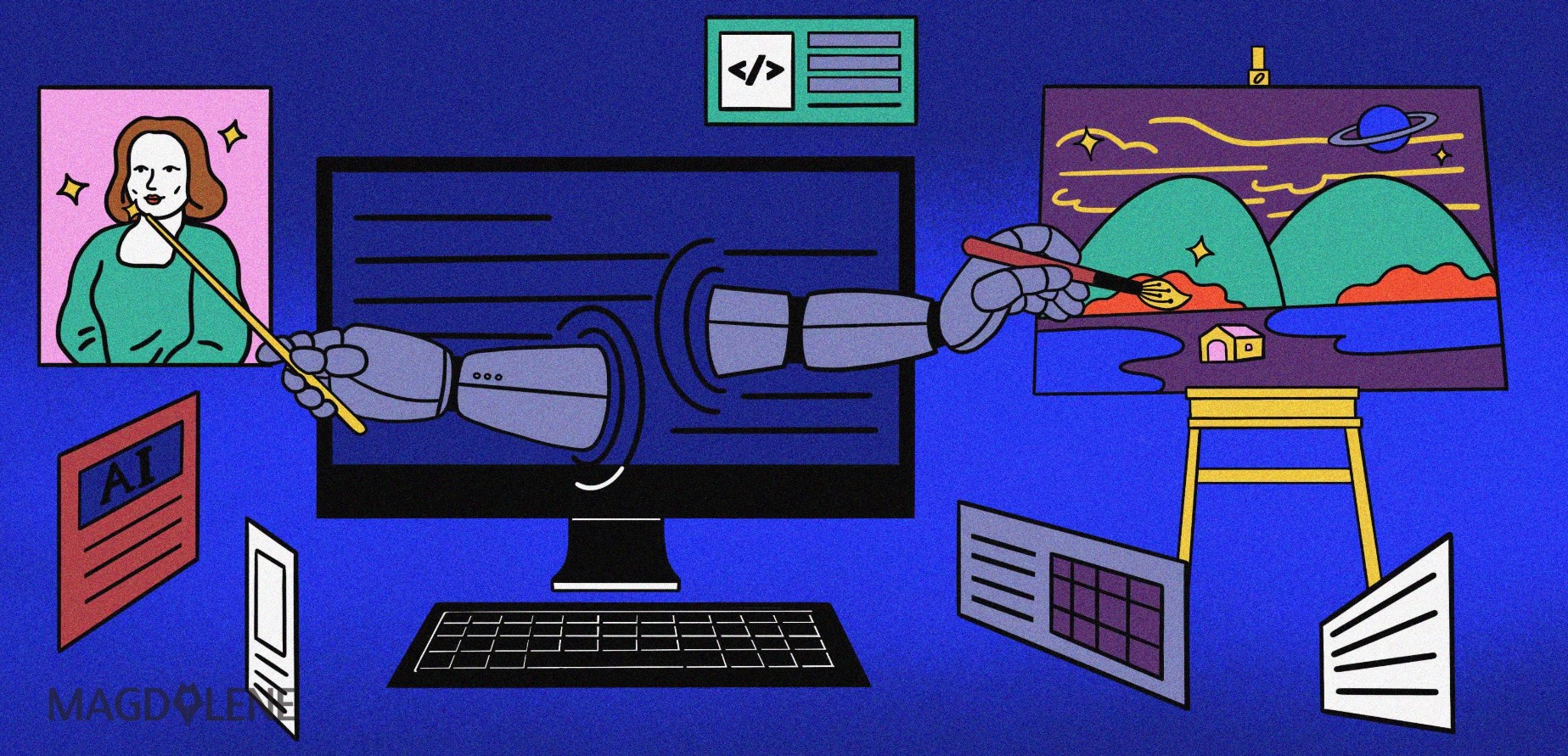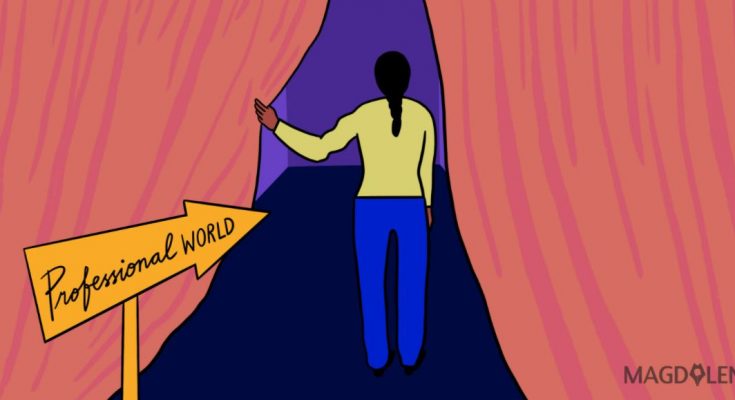Dian Eka Purnama Sari: Perempuan Pengusaha yang Lawan Stereotip
Dian Eka Purnama Sari adalah perempuan pengusaha berusia muda yang kini sedang sibuk mengembangkan sebuah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) miliknya, yang sebelumnya masih dikelola oleh kedua orang tuanya.
Alih-alih memilih banyaknya alternatif pekerjaan yang ditawarkan kota-kota besar bagi lulusan universitas seperti dia, perempuan 23 tahun itu malah mengambil jalan berliku penuh tantangan di lingkaran ekonomi dengan spektrum lokal, yakni di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam semangat yang dibawanya, Dian ingin memulai terobosan digital dari pelaku UMKM, yang menurutnya tidak banyak dilakoni oleh pengusaha Lombok.
Baca Juga: Martha Tilaar dan Wulan Tilaar Berbisnis dengan Empati, Selamatkan Pekerja
Ketergantungan para pelaku UMKM pada acara-acara kerajinan yang diselenggarakan pemerintah–dan kini agak sepi karena pandemi–membuat banyak UMKM perlu memutar otak dalam bertahan di situasi penuh kemungkinan ini. Tak jarang, Dian harus terjebak dalam perdebatan dengan orang tuanya yang masih menganggap pasar digital belum hal yang sekarang mesti disentuh.
Pengusaha Perempuan Di Balik Brand Ketak Nusantara

Dian adalah sosok yang pengusaha muda yang kritis meski terkadang cenderung “gegabah.” Ia pun akhirnya tetap memasuki pasar digital dengan Ketak Nusantara, sebuah brand UMKM yang mengembangkan karya-karya fashion dan berbagai furniture dengan bahan dasar rumput alam bernama Ketak. Berbeda dengan rotan–meski keduanya masuk dalam kategori tanaman paku-pakuan, ketak lebih kuat dan tahan lama. Bila rotan akan mudah lapuk setelah terkena air, ketak justru sebaliknya—akan semakin kuat dan antik seiring perjalanan usianya.
Dalam semangatnya, Dian tak sekadar ingin karyanya dibeli. Lebih daripada itu, ia ingin memosisikan karyanya sebagai simbol perjuangan, terutama bagi para korban perundungan dan terkhusus para perempuan yang sering kali berada pada level terancam.
Baca Juga: Anne Patricia Sutanto Pebisnis Tangguh yang Bertahan di Tengah Pandemi
“Saya tidak ingin sekadar karya saya dibeli, lantas sudah, apa lagi? Ada hal yang ingin saya kampanyekan, yakni betapa pentingnya mental yang sehat, dan betapa pentingnya perempuan yang independen,” ujar Dian, yang lulus dari Politeknik Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung jurusan Tenaga Penyuluh Lapangan itu.
Menurut Dian, nasib karya-karya UMKM dan posisi perempuan memiliki kesamaan. Selama ini, setidaknya dalam ukuran pengalamannya, karya-karya UMKM sering kali dipandang sebagai karya-karya yang kolot, serta sulit berinovasi dan beradaptasi dengan modernitas. Sekadar kerajinan yang tak memuat unsur estetik. Semacam ada aturan tak tertulis di lingkungan konsumen industri kreatif modern bahwa karya UMKM jauh dari kebutuhan zaman. Hal ini mengakibatkan UMKM bergerak di tempat yang “itu-itu melulu”.
Merespons stereotip ini, Dian melakukan riset secara mandiri, demi mengembangkan inovasi dan konsep yang melampaui anggapan-anggapan itu. Bukan sekadar karya yang dibutuhkan zaman, ia pun secara selektif memilih bentuk karya yang akan dianyamnya–begitu juga serta filosofinya. Metode riset yang diterapkan Dian pun terbilang sederhana dan unik. Ia mengajak perempuan-perempuan yang pernah menjadi korban perundungan karena ekspresi fashion-nya dianggap buruk. Perempuan-perempuan itu diberikan ruang untuk berpendapat, dan dari pendapat merekalah, Dian mengembangkan berbagai konsep.
Salah satu karya yang dibuatnya diberi nama Katana, yakni pedang tradisional di Jepang, Dian mengembangkan sebuah konsep pada karyanya yang menghasilkan tas dengan pola melengkung pada sudut-sudutnya. Pedang katana di Jepang merupakan simbol untuk memperjuangkan keadilan, juga digunakan oleh perempuan-perempuan Jepang zaman dulu untuk melindungi dirinya saat sedang terjebak dalam situasi yang berbahaya.
Sosok Dian Eka Purnama Sari yang Peduli Dengan Isu Gender dan Kesehatan Mental
Dian berharap, Katana buatannya dapat memiliki arti filosofi yang sama dengan yang ada di Jepang; menjadi simbol keadilan, terutama bagi perempuan yang sering kali menjadi korban perundungan lingkungan patriarki yang membatasi ekspresi fashion bagi setiap gender. Dian ingin Katana bisa menjadi milik siapa saja, dan berekspresi dengan bagaimana saja.
Selain isu gender, pebisnis perempuan ini pun mengampanyekan persoalan kesehatan mental yang menurutnya tak kalah penting. Menurut Dian, kebanyakan orang yang memiliki gangguan kesehatan mental adalah perempuan.
“Saya mengatakan ini bukan tanpa alasan, saya pernah berada di posisi itu. Saya berhasil lepas karena memang saya merasa sudah lelah, dukungan dari lingkungan yang sehat itu memang penting. Walaupun saat ini banyak yang meremehkan dan menganggap gerakan yang berkutat pada gerakan kesehatan mental atau pun gender sudah seperti polusi,” tegasnya.
Baca Juga: GOLD ISMIA Bantu Perempuan Penambang Emas Kurangi Risiko Penggunaan Merkuri
Pengusaha perempuan muda ini yang ternyata dulunya pernah menjadi seorang santri di sebuah pondok di Lombok, memahami betul semua situasi yang dihadapinya. Dian, dari apa yang diketahuinya di masa lalu, dan apa yang didapatkannya di masa sekarang, memberikannya semacam modal pengetahuan penting. Ia berhasil memformulasikan bagaimana seharusnya gerakan gender dalam industri fashion dihadirkan. Mengingat selama ini industri fashion dianggap sebagai penyumbang terbesar standar kecantikan.
Dian, di tengah ketabuan posisi perempuan dalam lingkungan ekonomi, kini sedang berhadapan dengan tantangan yang begitu besar. Di satu sisi ia berdiri sebagai pelaku UMKM, di sisi lain ia bergerak sebagai penyemangat bagi korban perundungan dan perempuan-perempuan yang membutuhkan kesetaraan. Dian bukan sekadar perempuan pengusaha, ia adalah orang yang terus bergerak melawan stereotip. Betapa pun sulit membayangkan konskuensinya.
“Sekali dayung, dua-tiga pulau harus dilewati,” pungkasnya.
Read More