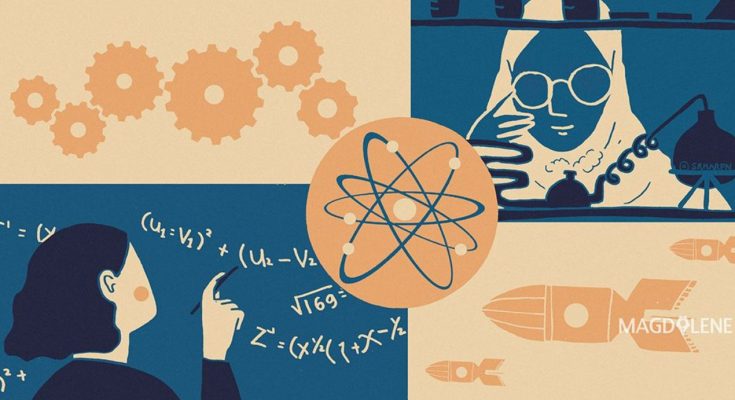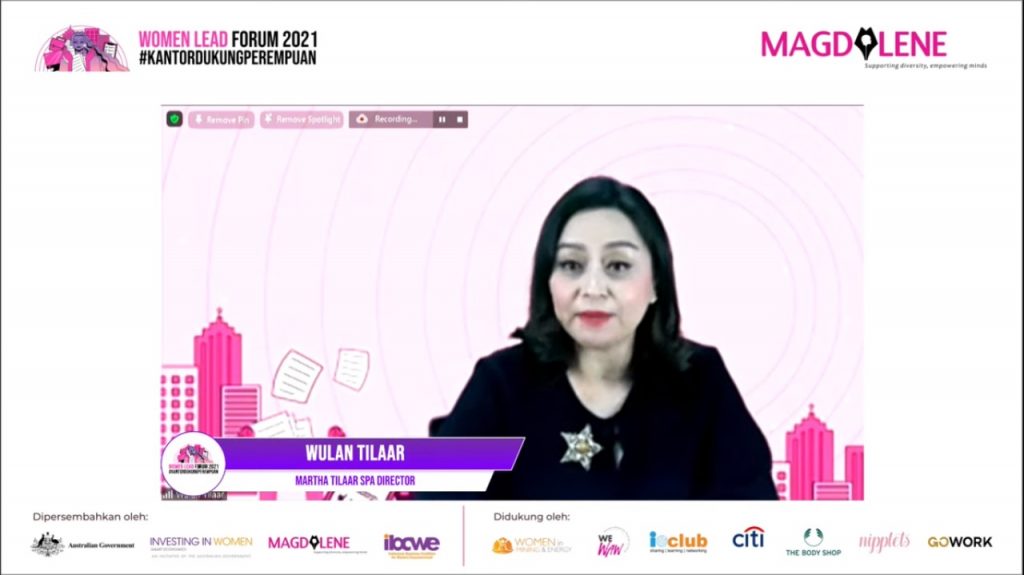Profil Ni Nengah Widiasih yang Raih Medali Pertama di Paralimpiade Tokyo 2020
Atlet Indonesia kembali berjaya di ajang olahraga tingkat internasional. Kali ini, nama Ni Nengah Widiasih, atlet disabilitas perempuan Indonesia yang berhasil menyabet medali perak di Paralimpiade Tokyo 2020, cabang olahraga Para Powerlifting kelas Women’s 41 kg dengan angkatan 98 kg pada (26/8). Angkatan terbaik itu berhasil Widi dapat pada percobaan terakhir atau ketiga, setelah berhasil menyelesaikan angkatan 96 kg pada kesempatan pertama, dan gagal menyelesaikan angkatan 98 kg pada percobaan kedua. Lewat pencapaian ini, Widi berhasil memperbaiki peringkatnya di Paralimpiade 2016 di Brazil, di mana ia berhasil meraih medali perunggu.
Ini bukan kali pertama perempuan asal Bali itu meraih prestasi gemilang dalam bidang olahraga. Banyak medali dari berbagai ajang olahraga telah berhasil diraihnya, dari medali emas di ajang Asian Para Games 2011 di Indonesia, medali emas di ASEAN Para Games 2015 di Singapura dan ASEAN Para Games 2017 di Malaysia, medali emas di World Para Powerlifting World Cup 2021 di Bangkok, dan masih banyak lagi.
Perjuangan Widi di Paralimpiade Tokyo 2020 sebenarnya tidak mulus. Pernyataan wasit yang menyebutnya gagal pada percobaan kedua dengan angkatan 98 kg nyaris bertentangan dengan kenyataan. Dia dinilai mampu mengangkat beban 98 kg-nya dengan baik, hanya saja itu tidak mulus dan membuatnya didiskualifikasi. Widi dan pelatihnya merasa tidak puas hingga sempat berniat mempertanyakan keputusan tersebut. Namun, akhirnya mereka mengurungkan niat dan baru akan protes jika angkatan ketiganya dinyatakan gagal juga.
Baca juga: Perempuan Indonesia Catat Sejarah, Emas buat Apriyani-Greysia
Setelah semua atlet menyelesaikan angkatan kedua, Widi menduduki peringkat ketiga dan hanya berpeluang meraih medali perunggu. Sementara itu, posisi kedua ditempati oleh atlet asal Venezuela, Monasterio Fuentes dengan angkatan 97 kg. Ni Nengah Widiasih tak menyerah, hingga ia berhasil menyelesaikan angkatan ketiga 98 kg dengan sempurna. Namun, tak lama setelah angkatannya selesai, wasit kembali mendiskualifikasi angkatannya karena dinilai tidak mulus. Hal itu membuat pelatih Widi langsung menghampiri wasit dan mempertanyakan keputusannya.
“Pelatih langsung meminta untuk tayangan ulang angkatan saya diputar ulang dan melihat apa kesalahan saya. Setelah melihat video review, akhirnya dewan wasit menyatakan angkatan saya mulus dan tangan saya tidak miring, sehingga dewan wasit mengesahkan angkatan saya,” ujar Widi.
Kemudian, Fuentes yang hanya unggul satu kilogram darinya gagal melakukan angkatan ketiganya seberat 99 kg. Hala itu membuat posisi Ni Nengah Widiasih terdongkrak naik ke posisi kedua. Widi pun berhasil meraih medali perak, sementara Fuentes medali perunggu. Dari sini, jalan Widi untuk meraih medali perak terbuka lebar setelah Fuentes gagal melakukan angkatan ketiga seberat 99 kg. Hasil buruk Fuentes otomatis mendongkrak posisi Widi naik ke urutan kedua. Widi meraih perak, sedangkan Fuentes mendapatkan perunggu.
Perjalanan Widi menjadi atlet yang berhasil berkecimpung di ajang-ajang olahraga dunia tidak mudah. Pada 2012 lalu, Widi ingin bisa berlaga di Paralimpiade London. Sebagai ajang latihan, ia ingin bisa berlaga di Kejuaraan Dunia di Dubai. Namun, Widi mengalami keterbatasan dana, sehingga itu membuatnya harus bekerja ekstra keras mencari pihak sponsor yang mau mendanainya. Untunglah, tiga minggu menjelang penutupan pendaftaran, Widi dan Komite Paralimpik Nasional Indonesia (NPC Indonesia) berhasil mengumpulkan sponsor yang mau mendanainya. Tak sia-sia, usaha Widi berbuah manis. Ia berhasil membawa perunggu pada kejuaraan dunia tersebut.
Baca juga: Sepak Bola Perempuan Semakin Diminati, Namun Disparitas Tetap Ada
Ni Nengah Widiasih Sempat Mengalami Krisis Kepercayaan Diri karena Disabilitas
Widi sudah beraktivitas di kursi roda sejak usianya masih tiga tahun. Ia didiagnosis mengidap polio yang membuat ukuran kakinya kecil sehingga tak bisa berjalan atau beraktivitas normal dengan kakinya. Hal itu sempat membuat Widi kehilangan kepercayaan diri. Terlebih, sewaktu kecil, dia hanya bisa melihat teman-temannya bermain, tapi tak bisa ikut bermain. Suatu ketika, Widi kecil pulang ke rumah sambil menangis ke pelukan orang tuanya.
“Waktu kelas satu atau dua SD, aku lupa. Saat itu pulang sekolah, aku menangis dan memeluk kedua orang tuaku. Aku tanya sama ayah, kenapa aku berbeda? Kenapa kakiku tidak bisa berfungsi selayaknya anak-anak, sih? Kenapa kakiku kecil? Kenapa aku enggak bisa jalan, enggak bisa berdiri?” ujar Widi dalam sebuah wawancara.
Hati orang tua Widi pilu. Setiap hari, keduanya selalu memberikan dukungan dan kekuatan untuk meyakinkan Widi bahwa perbedaan fisiknya bukanlah penghambat atau penentu keberhasilan.
“Ayahku pernah bilang, ‘Kamu tidak berbeda, kamu spesial. Mungkin, saat ini kamu belum mengerti dan memahami apa yang terjadi denganmu, dengan kakimu. Tapi, saat kamu dewasa, kamu akan mengerti dengan baik’,” ujarnya.
Widi pun mulai menemukan ketertarikannya di bidang olahraga pada waktu duduk di bangku sekolah dasar (SD). Saat itu, Widi pernah iseng-iseng ikut perlombaan olahraga balap atletik. Widi lalu mulai mengikuti beberapa perlombaan seperti Pekan Olahraga Pelajar Cacat (Popcat) dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN).
Baca juga: Berlapis Tekanan, Kesehatan Mental Atlet Diabaikan
Di tengah perjalanan, Ni Nengah Widiasih yang dikelilingi orang-orang yang menekuni olahraga angkat besi, terutama kakaknya, banting setir dan mulai menekuni cabang olahraga tersebut. Ketika mengikuti sebuah perlombaan, tak disangka, Widi berhasil mendapat juara, hingga meraih medali emas pertamanya di Kejuaraan Nasional tahun 2006.
Pada tahun 2007, Widi ditarik untuk mengikuti pelatnas di Surakarta, Jawa Tengah, di mana ia bersiap untuk mengikuti ASEAN Para Games di Thailand. Di ajang tersebut, Widi berhasil membawa pulang perunggu.
“Tentunya, menjadi atlet angkat berat ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi dengan menjadi atlet angkat berat ini saya menjadi perempuan yang kuat. Dulu, saya tidak mengetahui apa yang saya akan lakukan dengan kondisi saya yang saya kira mengurangi kapabilitas saya. Tapi dengan menjadi atlet, kelemahan yang dalam diri saya dapat menjadi kekuatan. Karena untuk menjadi atlet angkat berat membutuhkan energi yang luar biasa,” ujar Widi.
Dalam pidato kemenangannya pada Paralimpiade Tokyo 2020, Widi juga menyampaikan harapan agar pemerintah tidak membedakan penghargaan bagi atlet dengan disabilitas dan atlet non-disabilitas.
“Atlet disabilitas juga selalu bekerja keras dan berlatih dalam waktu yang sangat lama,” kata Widi.
Dalam ajang Paralimpiade Tokyo yang berlangsung sejak (22/8) sampai dengan (5/9), Indonesia mengirimkan 23 atlet dengan disabilitas. NPC Indonesia menargetkan kontingen Indonesia dapat membawa pulang satu medali emas.
Read More