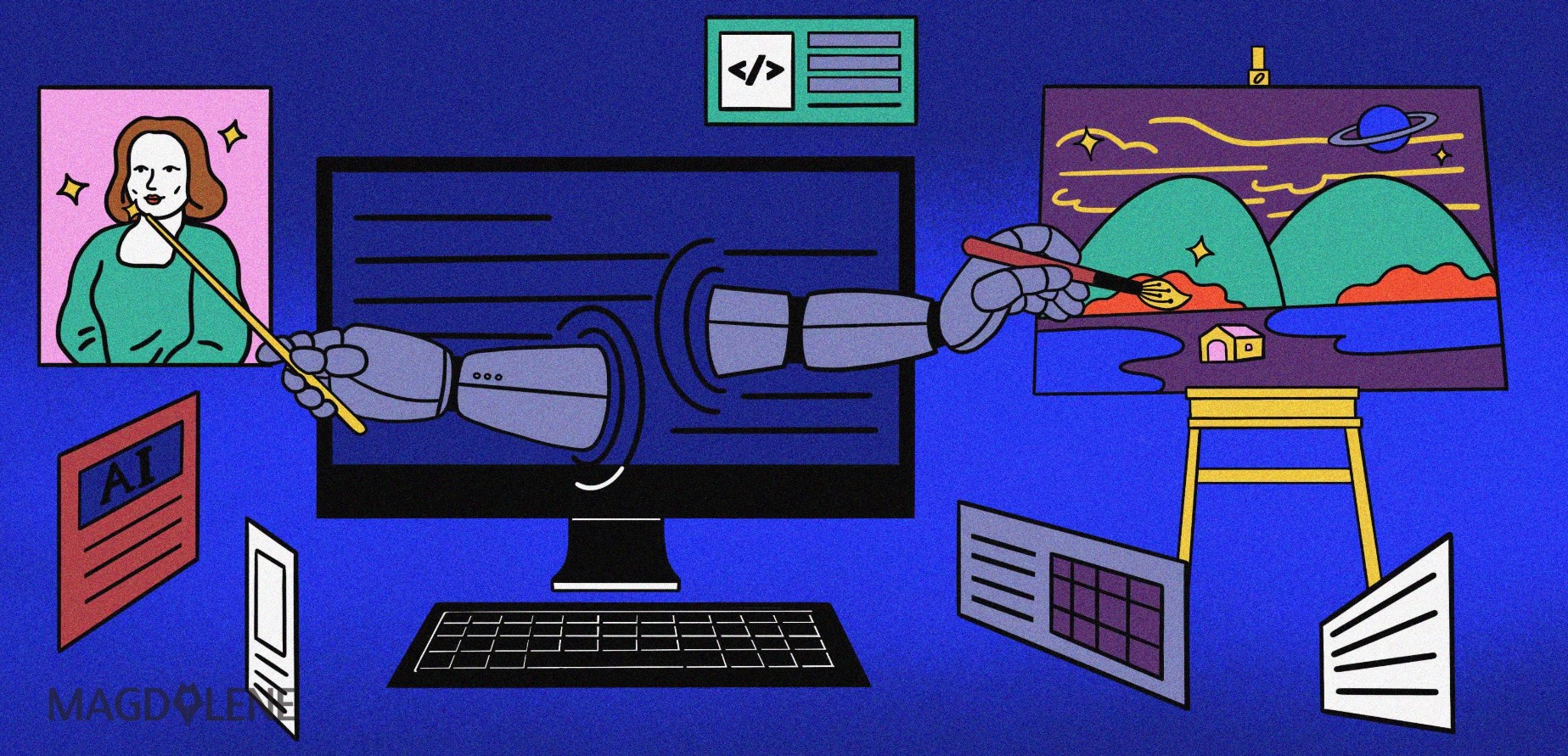Habis WFH Terbit ‘Workcation’, Ini Fakta-fakta yang Perlu Kamu Tahu
Kamu merasa jenuh bekerja dan bosan dengan WFH selama pandemi corona? workcation bisa jadi solusi untuk kamu. Apa itu workcation? Workcation atau work and vacation merupakan sebuah kegiatan mengunjungi destinasi tertentu untuk berlibur mencari suana baru sekaligus bekerja. Umumnya pekerjaan tersebut bersifat fleksibel, bisa dikerjakan kapan saja, di mana saja dengan dukungan koneksi internet yang baik.
Dikutip dari BBC, workcation tersebut sedang dipertimbangkan oleh banyak pekerja AS dan kanada yang sedang WFH. Haruskah kita mengikuti tren tersebut?
Mengapa Workcation Kedepannya akan Jadi Tren?
Seperti yang disebutkan di atas, workcation dapat jadi solusi kejenuhan bekerja secara jarak jauh karena pandemi. Bekerja dengan suasana baru dianggap lebih menyenangkan dari biasanya. Itulah mengapa, kegiatan ini kemungkinan besar akan jadi sebuah tren.
Baca Juga: ‘Burnout’ di Tempat Kerja, Ini Ciri dan Tips Mengatasinya
Mengapa Tidak Langsung Cuti Saja?
Mungkin beberapa orang akan berpikir bekerja sambil liburan, bukannya malah jadi tidak fokus? Pikiran jadi terbagi antara harus menyelesaikan pekerjaan, dan sebagian lagi membayangkan kegiatan lain yang menyenangkan yang dapat dilakukan di tempat wisata.
Walau begitu, nggak berarti workcation jadi kegiatan yang buruk. Supaya kamu tetap fokus dalam menyelesaikan pekerjaan, ada beberapa syarat yang harus kamu lakukan.
Dikutip dari Themuse.com, jangan berpikir workholiday itu sama dengan liburan saja. Kamu harus melihat kegiatan ini sebagai penghilang kejenuhan.
Kamu dapat bekerja dengan ditemani pemandangan baru, tanpa menghilangkan jatah cuti tahunan kamu. Tenang saja, kamu tetap bisa merasakan liburan dan sejenak melupakan pekerjaan kantor di luar jam kerja.
Tips Melakukan Workcation Supaya Lebih Menyenangkan
Sekarang kita bahas beberapa tips untuk melakukan workcation. Yuk kita simak apa saja.
Cari Lokasi yang Tepat untuk Workcation
Tips pertama kamu harus tentukan lokasi workcation yang tepat. Dalam tahapan ini, kamu harus ingat, workcation boleh dijalani sambil rebahan dan minum es kelapa muda di pinggir pantai, tapi kamu harus tetap bekerja ya.
Menurut Themuse.com, kamu harus hindari tempat wisata yang banyak destinasi menarik. Sebab, kemungkinan kamu bisa kunjungi destinasi tersebut bisa batal, karena kamu harus menyelesaikan pekerjaan.
Baca Juga: ‘Love-Hate Relationship’ dengan Pekerjaan, Haruskah Karyawan Bertahan?
Sebagai saran, ini ada beberapa saran yang bisa kamu pilih:
- Cari tempat dengan suasana yang tenang serta nyaman, dan kamu juga harus mencari tempat yang mempunyai koneksi internet bagus.
- Main ke tempat saudara atau teman di kota lain, jadi kamu bisa sekalian mengunjungi mereka di waktu luang.
- Cari tempat yang punya destinasi wisata yang tidak terlalu banyak namun menarik.
Intinya, cari destinasi yang cocok dengan tujuanmu, yaitu tempat untuk bekerja sambil liburan.
Atur Jadwal
Selanjutnya, kamu harus membuat jadwal yang jelas. Kamu tentukan waktu kamu harus bekerja dan waktu untuk kamu jalan-jalan. Buatlah jadwal tersebut dengan matang ya.
Walau kadang kita bisa keluar dari jadwal yang sudah ditentukan, paling tidak saat kamu sudah mempunyai jadwal akan mencegah kamu membuang waktu. Kamu pun jadi tidak merasa cuma pindah lokasi kerja, tetapi dapat memakai waktumu untuk sedikit bertualang.
Buat Persiapan Matang
Menurut Inc.com, workcation terasa lebih gampang kalau dilakukan oleh generasi Z. Pasalnya, kebanyakan dari mereka belum ada tanggungan, sehingga lebih fleksibel dan tidak perlu membuat persiapan rumit sebelum berangkat.
Walau begitu, bukan berarti kalau kamu punya anak dilarang kerja sambil liburan. Kamu cuma perlu menyiapkan workcation jadi lebih mendetail.
Kamu perlu pikirkan kira-kira siapa yang akan menjaga anak kamu saat sedang bekerja. Lalu, kapan waktu paling tepat untuk dapat berkunjung ketempat wisata. Tidak cuma untuk para ayah dan ibu, pemilik peliharaan juga perlu membuat persiapan. Pastikan ada yang menggantikanmu mengurus hewan kesayangan selama beberapa waktu.
Lakukan di Jadwal Kamu Sedang WFH
Kalau jadwal kamu harus ke kantor, kamu pastinya tidak mungkin dapat pergi ke tempat wisata dan bekerja dari sana. Jadi, lakukanlah workcation waktu kamu mendapat jadwal WFH.
Baca Juga: Dear ‘Fresh Graduate’, Siapkan Hal Ini untuk Masuk ke Dunia Kerja
Kamu yang sekarang masih setiap harinya bekerja dari rumah atau malah bebas bekerja darimana, tentu kamu bisa mencoba workcation.
Komunikasikan dengan Rekan Kerja
Poin kelima ini penting karena kamu harus bertanggung jawab dengan pekerjaan di kantor. Sebagai pekerja yang profesional, kamu seyogyanya menginfokan ke rekan yang lain kalau kamu akan liburan nyambi bekerja beberapa hari.
Kamu dapat memperlihatkan juga jadwal yang sudah kamu buat nantinya. Tujuannya supaya mereka dapat membantu menangani tugasmu di kantor untuk beberapa waktu ke depan. Tetap jaga komunikasi dan saling perbarui kabar dengan teman demi memperlihatkan kalau kamu tetap berkontribusi.
Jaga Diri dengan Vaksin dan Patuhi Protokol Kesehatan
Status pandemi Corona belum berakhir. Jadi, demi menjaga diri serta orang di sekitar, segera vaksinasi di klinik terdekat. Jadi, kamu akan jadi lebih tenang saat menjalani workcation.
Nah, jika kamu sudah mendapatkan dosis vaksin lengkap? Tetap jangan lengah, kamu tetap harus jaga protokol kesehatan selama liburan nantinya. Sebab, sebagaimana dikutip dari Cdc.gov, kendati kamu sudah vaksin, kamu tetap bisa terkena COVID-19 dengan pelbagai gejala ringan. Bahkan kamu tetap bisa berpotensi menularkan virus Corona ke orang lain.
Read More