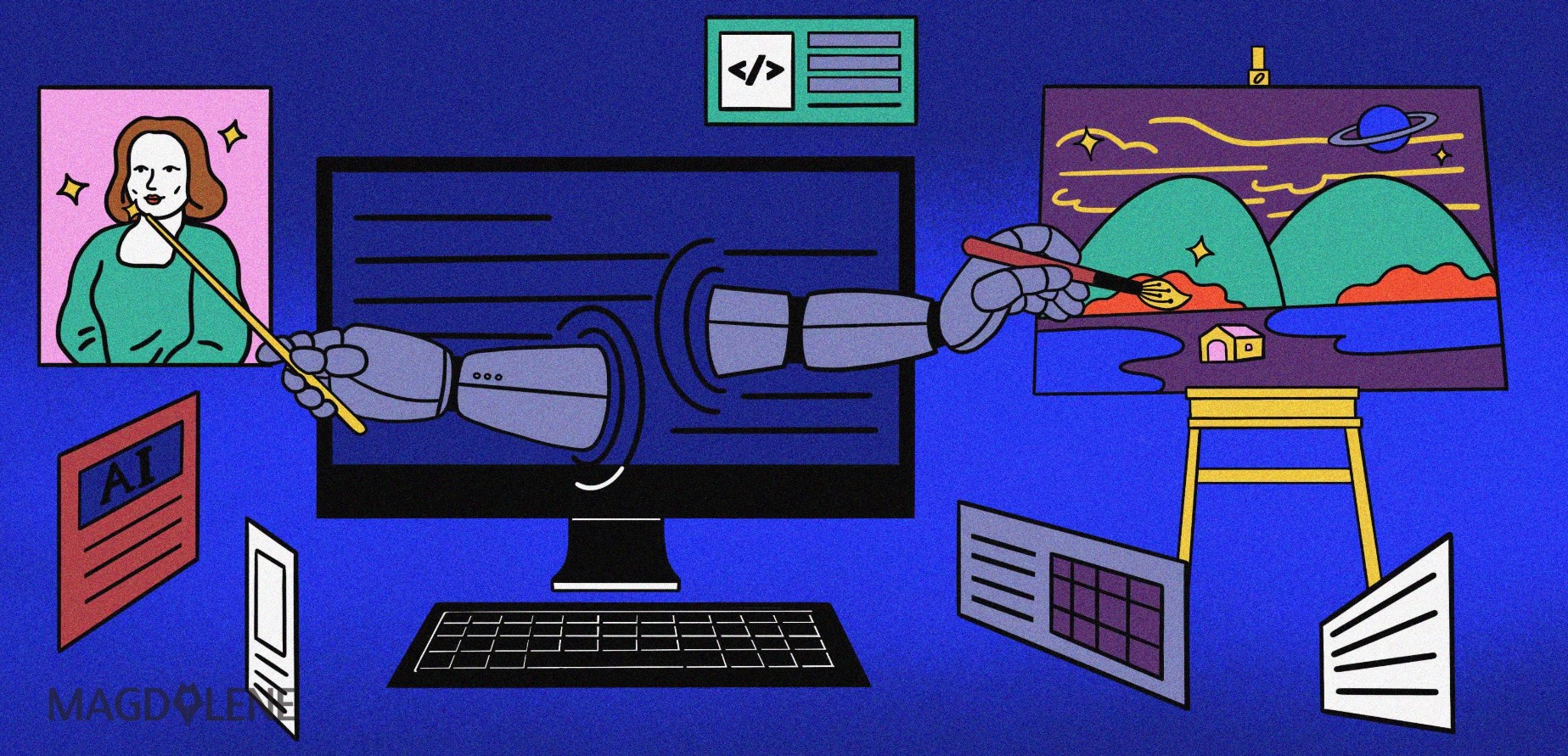Kenapa Ada Perempuan Takut Sukses, Bagaimana Mengatasinya?
Sejak kecil, “Fina” senang sekali menulis, mulai dari puisi, cerpen, hingga novel. Bahkan sejak remaja, ia kerap mengikuti berbagai kursus penulisan untuk mengasah kemampuannya. Karya-karyanya kerap diapresiasi teman-teman Fina, bahkan sebagian di antaranya membuat Fina jadi pemenang berbagai lomba.
Namun, apresiasi serupa tak didapatkannya dari keluarga, yang menganggap kegiatan menulis tak begitu penting dan tak menjamin kehidupan seseorang di kemudian hari. Kendati sudah terbukti karyanya cukup baik hingga memenangkan lomba, Fina berulang kali berpikir hal tersebut tidak lebih dari suatu keberuntungan.
Beranjak dewasa, Fina mengambil profesi sebagai jurnalis. Memang, ini sedikit bergeser dari minatnya terhadap dunia fiksi sejak dulu, tetapi Fina tetap menikmati perannya tersebut karena masih sejalan dengan kegemarannya menulis. Bos Fina melihat perkembangan perempuan tersebut dari waktu ke waktu dan kemauan Fina yang kuat untuk terus belajar. Karenanya, ia menawarkan Fina untuk menempati jabatan lebih tinggi di perusahaan.
Alih-alih gembira dan menerima kesempatan yang ditawarkan, Fina merasa cemas dan ragu saat mendapat promosi kerja. Ia masih merasa tidak layak memimpin teman-temannya di kantor dan membayangkan ia tidak sanggup mengemban tanggung jawab lebih besar saat itu. Pasalnya, saat mendapat promosi, Fina sudah berkeluarga dan anaknya masih balita.
Sebagian perempuan takut sukses sebagaimana Fina. Kita sering mendengar banyak orang takut gagal, sehingga mungkin berpikir ketakutan akan kesuksesan bukanlah hal nyata. Namun, sejumlah studi telah menemukan fenomena semacam ini dan menyelisik berbagai penyebab di baliknya.
Baca juga: Bagaimana Stereotip dan Norma Gender Mematikan Kepercayaan Diri Perempuan
Alasan Perempuan Takut Sukses
Konsep ketakutan akan kesuksesan (fear of success/FOS) pertama kali diperkenalkan oleh psikolog AS Matina Horner pada 1968. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan perbedaan perilaku terhadap pencapaian yang dipengaruhi perbedaan jenis kelamin.
Dilansir Encyclopedia.com, pada 1964, Horner membuat penelitian terhadap 90 mahasiswi dan 88 mahasiswa. Ia meminta mereka untuk menyelesaikan cerita tentang karakter “John” dan “Anne” yang keduanya merupakan mahasiswa kedokteran. Sebesar 90 persen mahasiswa menyelesaikan cerita dengan keberhasilan John yang diiringi dengan kebahagiaan dan kesejahteraan.
Sementara, 65 persen mahasiswi melihat masa depan Anne lebih negatif. Dari komentar para mahasiswi, Horner menyimpulkan, pada diri perempuan terdapat kecemasan tinggi bila mereka meraih kesuksesan karena mereka tidak bisa menjalani ekspektasi masyarakat. Perempuan yang sangat pintar, independen, atau ambisius dianggap tidak feminin, sehingga kesuksesan setara dengan laki-laki pun mereka hindari.
Di dalam negeri juga ada sejumlah riset tentang sebagian perempuan takut sukses, salah satunya yang diterbitkan dalam jurnal Palastren pada Juli 2019. Riset bertajuk “Fear of Success Perempuan Bekerja dalam Perspektif Budaya Jawa” ini menunjukkan, faktor budaya menyumbang FOS pada diri perempuan. Dalam budaya Jawa, perempuan dianggap sebagai kanca wingking bagi suami. Peran perempuan yang didefinisikan dalam budaya seperti ini membuat perempuan berhadapan dengan konflik antara mengejar pencapaian dan penyesuaian diri atas nilai-nilai budayanya agar tetap bisa diterima masyarakat.
Dalam riset tersebut dikatakan, alih-alih ketakutan akan pencapaian pada area yang lazimnya dipandang sebagai milik laki-laki (ranah publik), FOS lebih merupakan ketakutan pada konsekuensi negatif yang muncul akibat kesuksesan, dalam hal ini konsekuensi tersebut berupa penolakan sosial terhadap perempuan yang tak memenuhi peran sebagai kanca wingking.
Pada sebagian perempuan takut sukses, ditemukan pesimisme terhadap hal baik yang diterimanya. Bukannya memikirkan berbagai kesempatan dan keuntungan dari mencapai kesuksesan, mereka justru lebih berfokus pada kemungkinan terburuk yang bisa terjadi bila mereka mengambil kesempatan untuk sukses tersebut, seperti dalam contoh kasus Fina. Ia takut ia tidak bisa menjalankan peran sebagai ibu dan istri yang baik seiring bertambahnya tugas dari kantor, dan ia khawatir orang sekitar akan menghakiminya bila ia memutuskan mengambil kesempatan promosi.
Terlepas dari gender apa pun, ada alasan lain kenapa orang takut sukses. Dalam Forbes disebutkan, kekhawatiran akan kehilangan diri sendiri menjadi salah satu faktor penyebabnya. Banyak orang takut jika mereka sukses atau meraih banyak uang, ego mereka akan meninggi dan mereka menjadi orang berbeda yang lebih buruk.
Ada juga alasan takut menghadapi kritik ketika mereka ada di bawah sorotan. Tidak semua orang suka diperhatikan banyak orang dan siap untuk menghadapi suatu kritikan. Karenanya, mereka memilih mundur jika mereka mendapat kesempatan untuk menjadi lebih sukses.
Selain itu, FOS bisa juga dipicu oleh ketakutan akan kehilangan teman atau momen-momen berharga bersama orang terdekatnya. Ini dapat terjadi seiring meningkatnya beban kerja yang menuntut lebih banyak waktu dan energi, sehingga kesempatan untuk memiliki waktu berkualitas bersama orang terdekat harus terpangkas.
Baca juga: Masalah Kepercayaan Diri Masih Hantui Perempuan Pemimpin Bisnis
Dalam Psychology Today, terapis pernikahan dan keluarga Susanne Babel menulis, banyak orang percaya bahwa jalan menuju kesuksesan melibatkan berbagai risiko seperti naiknya harapan orang lain. Hal ini bisa memicu ketakutan tersendiri bagi seseorang, terlebih bila ia punya kecenderungan untuk menyenangkan orang lain dan tidak bisa menerima kekecewaan.
Terkait pengalaman Fina, ternyata pengalaman tak dihargai atau mengalami kekerasan verbal bisa juga berkontribusi terhadap FOS. Menurut Babel, orang-orang yang terbiasa disebut pecundang atau tidak diakui bisa menginternalisasi label seperti itu dalam dirinya sehingga kelak ia merasa tak layak sukses.
FOS bisa mendorong seseorang pada akhirnya menyabotase dirinya sendiri. Sekalipun ia punya kapabilitas, ia tidak akan tampil baik karena ia mau menghindari konsekuensi negatif seperti penolakan sosial terkait kegagalan memenuhi ekspektasi masyarakat. Ia juga mungkin mengambil tugas-tugas yang lebih mudah dicapai dan tidak memasang target lebih tinggi walaupun ia mampu.
Bagaimana Cara Mengatasinya?
Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan ketika menyadari bahwa kamu memiliki FOS. Pertama, kamu perlu mencari tahu dulu sumber FOS yang kamu rasakan. Apakah itu berasal dari pengalaman masa kecil, misalnya pencapaianmu tidak diakui keluarga, atau kamu pernah menerima ejekan dari orang lain atas karya kita. Lalu, kamu bisa mencoba mengkroscek pandangan mereka dengan orang-orang lainnya sehingga tidak satu suara negatif saja yang bergaung di kepalamu.
Jika sebenarnya karyamu mereka anggap cukup baik dan orang lain puas dengan kinerjamu, artinya kamu sebenarnya layak-layak saja untuk diakui dan menerima kesempatan untuk sukses. Jangan biarkan komentar negatif sebagian pihak langsung membuat dirimu rendah diri.
Selanjutnya, coba kenali “gejala-gejala” FOS kamu. Apakah kamu cenderung menunda pekerjaan? Apakah kamu menghindari dapat proyek besar meskipun kamu sanggup? Dalam Healthline disebutkan, membuat daftar gejala-gejala FOS-mu muncul bisa menghindarkan dari upaya menyabotase jalanmu untuk sukses. Mengidentifikasi perilaku-perilaku itu berarti kamu mulai berusaha untuk melawan FOS-mu.
Ketika kamu merasa begitu pesimis kamu mampu mengemban tanggung jawab lebih besar, kamu bisa mulai menggeser fokusmu dari kecemasan berlarut-larut akan mengecewakan orang dengan memikirkan apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Segala hal mungkin tidak akan terselesaikan sempurna, tetapi kamu tetap bisa berusaha menuntaskannya satu hal di satu waktu. Tak perlu berharap muluk-muluk kamu selalu bisa menyenangkan orang dan menghindari kritik. Lagi pula, kritik tak selamanya akan menjatuhkanmu kok. Itu bisa membuka jalan bagimu untuk bekerja dan menjadi pribadi yang lebih baik.
Read More