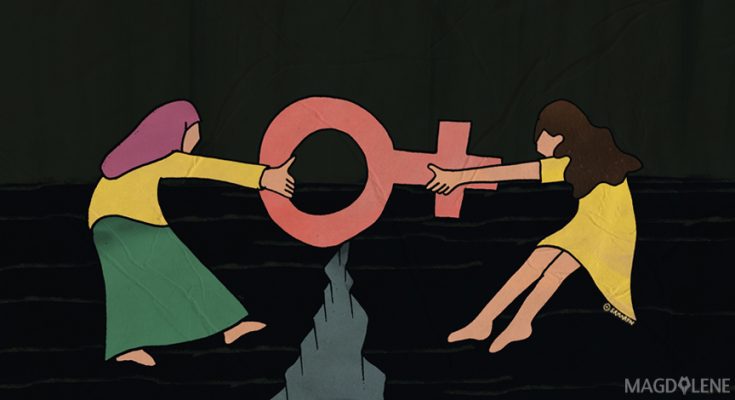Pemerintah menyatakan bahwa capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia telah mengalami peningkatan. Indeks ini merupakan parameter kesetaraan gender yang diukur dari sumbangan pendapatan perempuan melalui keterlibatan dalam parlemen, pengambilan keputusan, jabatan sebagai tenaga profesional, hingga ekonomi, mengalami peningkatan. Pada 2019 angka IDG mencapai 75,24, sementara pada 2020, IDG kita ada di angka 68,15.
Meskipun demikian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan bahwa angka tersebut merefleksikan belum ada partisipasi maksimal dan aktif dari perempuan dalam bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi secara spesifik.
“Ini disayangkan karena perempuan adalah setengah dari potensi bangsa sesungguhnya, termasuk potensi ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2020, angkatan kerja perempuan hanya mencapai 53,15 persen, sementara laki-laki 82,4 persen,” ujarnya dalam webinar “Choose To Challenge: Merayakan Keragaman Perempuan Bekerja”, (24/3). Webinar yang diselenggarakan Rumah KitaB tersebut bertujuan untuk mendorong lebih banyak perempuan muslimah untuk terjun dalam ranah profesional.
Ia menambahkan, peran perempuan dalam membangun kesetaraan gender di masyarakat sangat penting untuk mencapai poin kelima Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Hal ini menjadi fokus pemerintah untuk memajukan negara.
“Dunia sudah tidak menghendaki praktik eksklusivisme masyarakat. Masa depan adalah masyarakat demokratis, terbuka bekerja sama dengan setara,” ujar Bintang.
Direktur Eksekutif Rumah KitaB, Lies Marcoes menyatakan, selama masa pandemi COVID-19, perempuan bekerja mengalami banyak tantangan karena harus mengandung beban kerja ganda sekaligus. Beban ganda tersebut ialah tanggung jawab ekonomi sebagai pekerja dan seorang ibu.
“Perempuan juga merasa terhambat karena ada peran pengasuhan yang timpang. Ini menjadi tantangan bersama untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif gender,” ujarnya.
Sinta Nuriyah Wahid, Ibu Negara Republik Indonesia keempat, juga mengatakan pemerintah harus responsif pada perubahan untuk kesetaraan gender karena perempuan merupakan bagian kekuatan suatu keluarga.
“Untuk itu, hubungan pemerintah dengan masyarakat, sektor usaha, serta pandangan keagamaan harus ikut mendukung pilihan hidup perempuan, seperti masuk ke ranah kerja,” kata Sinta.
Meski demikian, masih banyak tantangan dan hambatan yang dialami perempuan untuk masuk dan ketika berada dunia profesional, tambahnya. Berikut ini empat hal yang menjadi penyebab perempuan sulit berkiprah di ranah profesional.
Baca juga: Women Lead Forum 2021 Kupas Hambatan Diskriminatif, Dorong Perempuan Pemimpin
1. Patriarki Timbulkan Stigma Pada Perempuan ingin Berkarier dan Pekerja
Budaya patriarki yang mengakar kuat di masyarakat terus menjadi penyebab akses pendidikan dan informasi yang dimiliki perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Paham konservatif sarat nilai patriarki yang mencari legitimasi dalam nilai keagamaan telah mempersempit kiprah perempuan di ranah kerja.
Nani Zulminarni, Regional Director Ashoka Southeast Asia mengatakan, untuk mendorong peran perempuan dalam berbagai sektor ranah profesional, nilai patriarki yang menyebabkan stigma perempuan berkarier atau pekerja sebagai individu yang tidak benar, melawan kodrat, dan tidak ideal untuk masuk surga, harus dilawan.
“Jika perempuan berpartisipasi secara setara dengan laki-laki dalam ekonomi, maka gross domestic product (GDP) global akan meningkat 26 persen tahun 2025,” ujarnya.
Nilai patriarki ini juga menghambat perempuan untuk berkarier dan mengetahui potensi yang dimilikinya untuk menduduki posisi strategis dalam suatu perusahaan.
“Hanya 12 persen perempuan yang sadar bahwa dia ingin menjadi CEO. Selebihnya baru sadar bahwa dia hebat dan luas biasa ketika ada orang lain yang mengatakannya. Perempuan tidak sadar akan potensinya karena selalu dicekoki sebagai sosok yang tidak mampu,” terang Nani.
Pada 2019, hasil riset ValueChampion, sebuah badan riset dan analisis data asal Singapura, menunjukkan bahwa Indonesia menduduki posisi kedua sebagai negara paling berbahaya untuk perempuan di Asia Pasifik setelah India. Diar Zukhrufah, seorang penulis untuk Communicaption, sebuah agensi konten digital, mengatakan masyarakat dengan paham nilai patriarkal akan menggunakan alasan Indonesia sebagai lingkungan tidak aman agar perempuan tidak bekerja.
“Kenapa perempuan harus merasa tidak aman di ruang publik? Padahal, yang salah bukan perempuan yang harus bekerja. Ini menjadi satu tantangan yang harus kita jawab,” kata Diar.
Savic Ali, pendiri Islami.co, situs yang berfokus pada isu toleransi dan kedamaian, mengatakan bahwa nilai patriarki menjadi isu struktural yang mengglobal. Untuk masyarakat Indonesia, nilai patriarki tersebut bersinggungan erat dengan ajaran keagamaan.
“Patriarki adalah masalah peradaban bukan untuk satu bangsa. Dalam konteks Indonesia, masyarakat religius Indonesia menganggap agama sangat penting sehingga banyak urusan yang merujuk pada agama,” ujar Savic.
Baca juga: Stereotip Gender dalam Periklanan Indonesia dan Global
2. Pembagian Tugas Domestik yang Timpang
Sinta Nuriyah mengatakan, peluang perempuan untuk berkarier dan ikut berkompetisi di ranah kerja kini memang sudah lebih besar. Meski demikian, perempuan masih terhalang oleh ketimpangan pembagian tugas domestik yang menyebabkan mereka kesulitan mengembangkan profesionalitas atau keahlian.
Jika perempuan tidak didukung oleh keluarga dalam menanggung beban rumah tangga, ia akan sulit mengakses kesempatan mengembangkan dirinya. Perempuan sulit menggunakan waktu terbatas yang ia miliki untuk meningkatkan kualitas dan etos kerja mereka, imbuh Sinta.
“Ini merupakan kesempatan sekaligus tantangan untuk perempuan. Pintu kerja akan tertutup kembali karena tenaga kerja perempuan tidak memiliki kualifikasi yang memadai akibat peran gender dan tugas domestik yang timpang,” jelas Sinta.
Nani mengatakan, ketimpangan dalam pembagian tanggung jawab domestik dan peran gender tidak lepas dari relasi kuasa dalam keluarga.
“Durasi kerja perempuan di ranah domestik tiga kali lebih lama dibanding laki-laki. Sedihnya, peran itu dianggap ‘bukan bekerja’,” ujarnya.
Anggapan bahwa tugas domestik hanya menjadi tanggung jawab perempuan menjadi basis kelompok fundamentalis untuk melanggengkan status quo. Selain itu, hal tersebut juga memberi stigma bagi perempuan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga sebagai perempuan yang tidak berperan, ujar Nani.
Ia menambahkan, pembagian tugas yang adil memberikan perempuan untuk mencari tahu tentang kemampuannya, berkontribusi di ranah publik, dan tetap bisa bertanggung jawab di rumah.
“Ranah publik dan domestik sama-sama menjadi tanggung jawab pasangan, sehingga pekerjaan menjadi lebih ringan dan perempuan bisa semakin produktif,” kata Nani.
Baca juga: Pelajaran dari ‘Buffy the Vampire Slayer” Soal Lingkungan Kerja Toksik
3. Terpapar Ajaran Ultrakonservatif di Internet
Nilai-nilai agama berperan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut hasil survei PEW Research Centre tahun 2008 hingga 2017, The Age Gap in Religion Around The World, 93 persen masyarakat muslim Indonesia menilai peran agama sangat penting. Angka tersebut naik menjadi 94 persen pada 2019.
Di era digital seperti sekarang, perempuan akan menelusuri internet untuk mencari informasi tentang pandangan agama terhadap perempuan yang bekerja. Savic mengatakan, perempuan yang mencari informasi tentang dalil agama lebih sering terpapar ajaran ultrakonservatif di media.
Ajaran tersebut memang tidak pro-kekerasan dan menghakimi kelompok lain. Namun, tetap mengandung pandangan konservatif yang menekankan bahwa perempuan seharusnya hanya di rumah.
“Jadi kalau mencari di Google soal hukum perempuan bekerja, yang muncul di halaman pertama adalah ajaran ultrakonservatif. Perempuan menjadi ragu untuk bekerja,” kata Savic.
Menurutnya, ajaran ultrakonservatif yang dangkal mulai bebas bermunculan di Indonesia sejak era reformasi.
“Harus diakui, sejak reformasi ada keterbukaan, masyarakat lebih beragam, namun terpecah belah. Diskursus tentang perempuan yang dulunya dikuasai negara menjadi dikuasai kelompok-kelompok agama. Akhirnya, ada keragaman pandangan terkait perempuan,” kata Savic.
Ia mengatakan, ajaran yang mengandung nilai ultakonservatif yang ditemukan di internet menjadi berbahaya jika pembaca tidak melihat situs atau artikel lain yang lebih moderat sebagai perbandingan.
“Umumnya ultrakonservatisme ini dari ajaran Salafi dan Wahabi. Menurut ulama ajaran-ajaran itu, perempuan sebaiknya di rumah saja. Kalau keluar, harus ditemani mahram karena di luar banyak fitnah, dan kehormatan perempuan akan terjaga kalau di rumah,” papar Savic.
4. Pemahaman Keagamaan yang Sempit dan Dangkal Hambat Perempuan Berkarier di Kantor
Pemahaman agama sempit dan dangkal atau ultrakonservatisme juga kerap ditemukan dalam dunia profesional yang dijalani perempuan. Savic menambahkan ajaran agama yang sempit tersebut diterima perempuan tidak hanya melalui internet, tetapi pada pengajian kantor.
Sinta Nuriyah mengatakan, ada sejumlah perempuan yang berhenti menjadi pekerja dan tenaga profesional setelah mengikuti gerakan hijrah.
“Ada di antara mereka [yang mengundurkan diri] yang telah menjabat di posisi strategis perusahaan. Mereka keluar karena alasan perintah agama dan mencari yang halal,” ujarnya.
Tidak hanya soal berhenti dari dunia kerja, menurut Savic, kuatnya pengaruh gerakan hijrah juga terlihat dari banyaknya narasi keagamaan yang mendorong perempuan untuk berjilbab, bahkan mengikuti standar tertentu dengan embel-embel “jilbab yang syar’i”.
Sinta menyayangkan banyaknya perempuan yang masih terbelenggu tafsir agama tertentu yang membuat mereka mengorbankan pekerjaannya, padahal kesempatan bagi mereka sudah terbuka.
“Cara pandang seperti ini menutup pintu kesempatan perempuan berkarya dan mengembangkan diri yang juga merupakan bagian dari perintah agama,” kata Sinta.