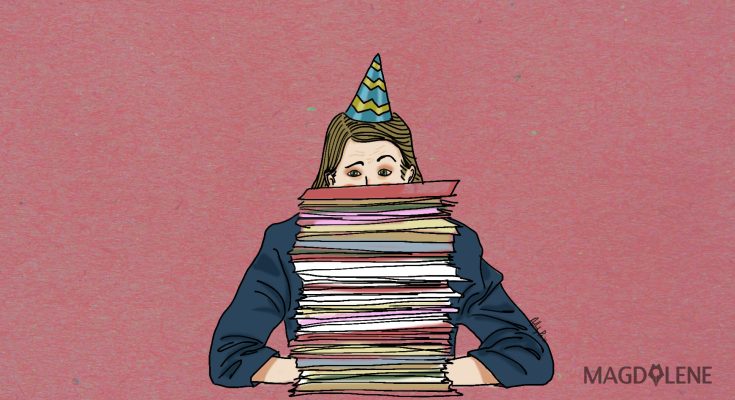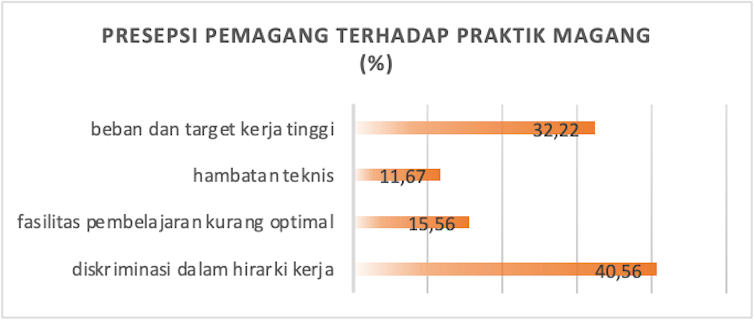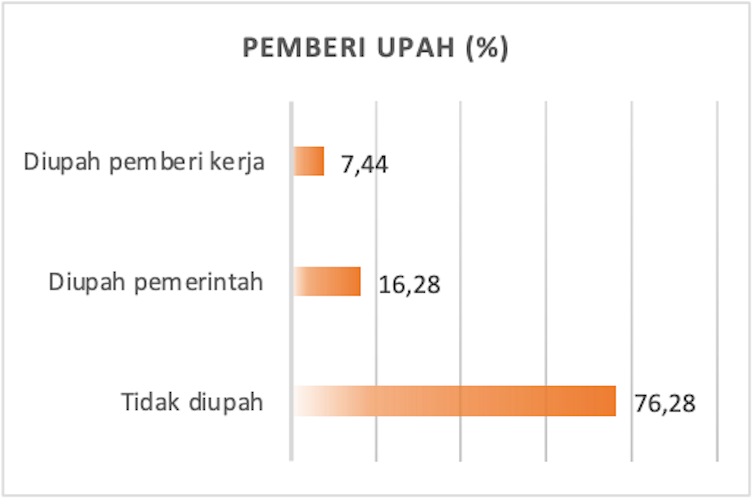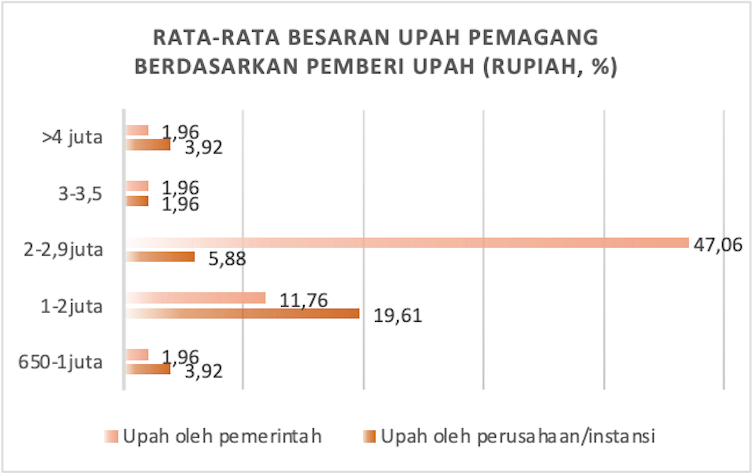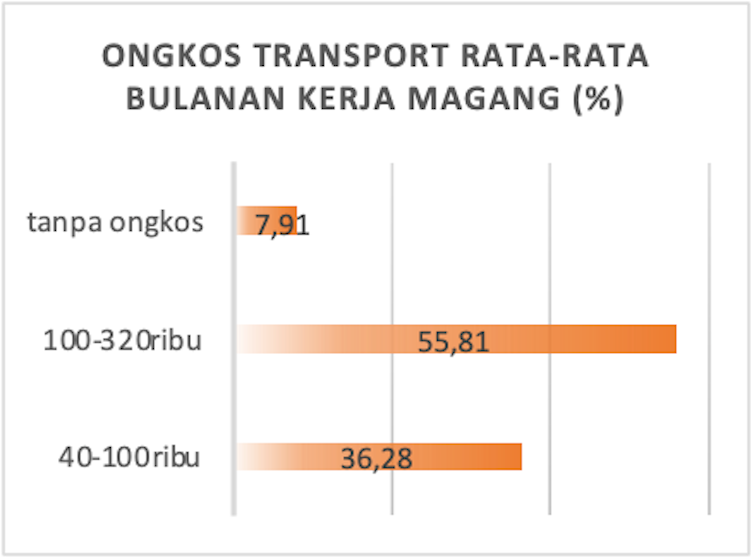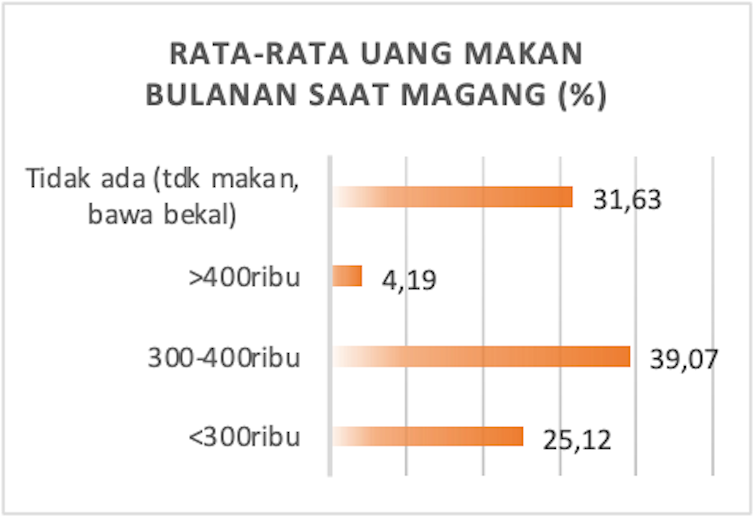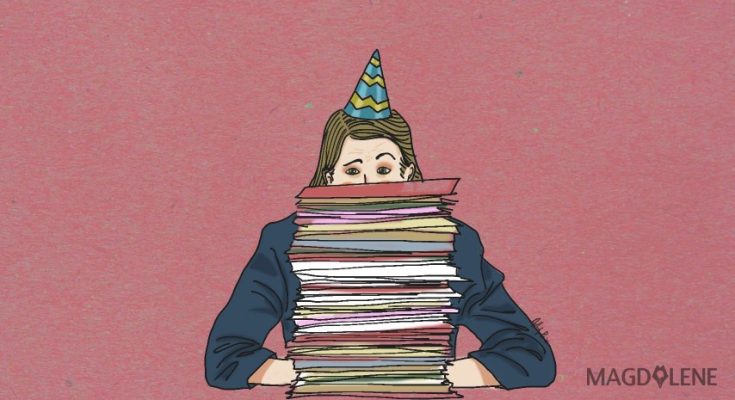‘Bye Job Hopping, Halo Job Hugging’: Realitas Pasar Kerja Indonesia yang Kian Tak Pasti
Ini adalah tahun keempat “Andrea” bekerja di kantor yang sama. Selepas menamatkan strata satunya (S1), ia berkesempatan meniti karier di salah satu perusahaan swasta di Jakarta.
Seperti kebanyakan orang, mulanya Andrea senang lantaran beruntung bisa langsung mendapat kerja selepas kuliah. Tanpa proses yang sulit, ia bisa merasakan gaji pertama yang cukup dan tempat berkembang baru di usianya yang masih 20 tahunan.
Sayang, euforia mendapat pekerjaan tak berlangsung lama. Di tahun keempat, Andrea merasa kariernya stuck dan bingung mau melangkah ke mana. Lama-kelamaan ia memutuskan tetap bertahan demi melanjutkan hidup semata. Pengembangan diri jadi barang mahal yang sulit digapai karena ia tak bisa bergerak ke mana-mana.
“Gue sebenernya mempertahankan pekerjaan ini biar ada pemasukan aja, biar gue tetep hidup, gitu. Soalnya gue udah merasa apa ya? Stuck kali ya. Kayak bingung ini mau ngembangin diri kayak gimana lagi?,” kata Andrea.
Tak hanya Andrea, “Bima”, salah satu pekerja di badan usaha milik negara (BUMN) juga merasakan hal yang sama. Meskipun orang bilang pekerjaan yang ia dapat adalah cita-cita para orang tua, Bima belum merasa demikian. Setelah lebih dari tiga tahun bekerja di sana, ia tak punya alasan lain selain gaji untuk bertahan. Tak ada pengembangan diri yang signifikan, katanya. Mau mencari ke luar pun pilihannya tidak ada.
“Lebih ke sekarang opsinya enggak ada. Kalau mau pindah harus ke entry level lagi karena ketersediaan untuk level-level menengah gini hampir enggak ada. Bisa dibilang bertahan emang lebih aman,” ungkap Bima.
Seperti Andrea dan Bima, “Nisrina” pun punya keluhan yang sama. Hanya saja, keluhan Nisrina tak hanya soal karier yang stuck atau pengembangan diri yang nihil. Dalam kasusnya, Nisrina juga harus berhadapan dengan atasan yang toxic untuk bertahan hidup. Kerja lembur pun jadi makanannya sehari-hari.
“Kayaknya kalau enggak buat makan sehari-hari, aku better cabut sih dari kantor yang sekarang. Kerjaannya tuh betul-betul overload banget. Belum lagi atasan juga baperannya minta ampun. Rasanya enggak sepadan gitu gaji dengan apa yang dikerjain. Mau pindah tapi enggak juga ada pilihannya,” cerita Nisrina.
Belakangan pengalaman ketiga orang ini ramai dibahas di media sosial. Salah satu perusahaan aplikasi personalia di Amerika Serikat, Resume Builder, memotret fenomena ini sebagai job hugging. Maksudnya, para pekerja berupaya bertahan di posisi mereka kini, bukan karena loyalitas apalagi kepuasan kerja. Mereka cuma takut akan kehilangan pendapatan karena ketidakpastian pasar kerja.
Melansir CNBC, berbeda dengan job hopping yang sempat jadi tren di Indonesia pada 2021-2022 lalu, job hugging merupakan fenomena di mana pekerja tidak punya pilihan untuk meningkatkan karier mereka. Akibatnya, mereka pun hanya berupaya menikmati pekerjaan yang sekarang–meski tanpa pengembangan diri, dan bahkan harus menelan lingkungan kerja yang juga tidak sehat.
Baca juga: Ijazah ‘Wah’, Cari Kerja Susah: Di Balik Maraknya Pengangguran Gen Z
Bergelut di Antara Rasa Aman dan Karier yang Stagnan
Di Amerika, survei Resume Builder menemukan bahwa hampir setengah pekerja di sana berada dalam kondisi job hugging. Mereka yang memeluk pekerjaannya bilang, bertahan adalah pilihan yang paling masuk akal dan aman di tengah situasi yang tidak pasti. Sebagian dari mereka bahkan berupaya keras untuk mempertahankan posisinya saat ini. Upaya tersebut termasuk menelan jam kerja yang berlebih, sampai mengambil tugas tambahan dari rekan kerja yang lain.
Meskipun di Indonesia survei sejenis belum dilakukan, kisah Andrea, Bima, dan Nisrina, bisa jadi gambaran bagaimana pekerja di Indonesia juga tengah memeluk erat pekerjaannya untuk saat ini. Meskipun berat dan tidak dapat memberikan pengembangan diri, ketiganya bertahan setidaknya untuk menyambung hidup dari hari ke hari.
Celaka dua belas, rasa aman ini juga dibarengi dengan tekanan yang sering kali menyerang kesehatan mental. Pada Andrea hal ini bahkan berujung pada kelelahan emosional (burn out) yang hampir dirasakan setiap hari. Karena kerja untuk sekadar menjaga cashflow, Andrea bingung untuk memastikan apa yang benar-benar sedang ia kerjakan.
“I’m questioning myself, my purpose everyday. Gue merasa setiap hari itu berat. Kayak gue bikin to-do list nih, tapi jadi overwhelmed juga kalau enggak semua terselesaikan. Ujung-ujungnya jadi nyalahin diri sendiri, ‘kok gue nggak perform kayak dulu ya?’, gitu.”
Senada, bagi Bima bertahan untuk gaji sama saja dengan menggadaikan proses perkembangan kariernya ke depan. Bukan tidak bersyukur, sebutnya. Masalahnya Bima merasa kehilangan momentum untuk bertumbuh karena terpentok kesempatan kerja lain yang kosong dan usia yang terus bertambah. Ia pun kian merasa lesu ketika melakukan aktivitasnya sehari-hari.
“Mungkin tepatnya unfulfilled ya. Karena ya itu, merasa kehilangan banyak momentum aja untuk dapat kesempatan lain. Tapi di sisi lain, usia terus nambah,” katanya.
Kondisi ini pun dikonfirmasi Dr. Kaitlin Harkess, psikolog klinis, dalam wawancaranya bersama NT News pada (14/9). Ia bilang job hugging memang bisa menyebabkan kualitas hidup yang buruk, frustrasi, sampai gejala stres macam kelelahan dan kurang tidur.
Baca juga: Nasib Perempuan Pekerja: Batas Umur di Loker Lebih Merugikan Perempuan?
Bagaimana dengan Pekerja Perempuan?
Meskipun fenomena job hugging baru muncul belakangan, nyatanya, para pekerja perempuan tercatat sudah melalui rintangan ini jauh sebelum konsep tersebut ramai dibicarakan. Hariati Sinaga, Dosen Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia, bilang hal ini berkaitan dengan stigma dan bias di dunia kerja yang sudah ada sejak dulu.
Ia bilang mayoritas perempuan memang terpaksa bertahan pada pekerjaannya karena tak banyak pilihan yang bisa dicoba untuk mencari peruntungan. Banyaknya syarat yang tercantum dalam lowongan pekerjaan jadi penyebab mengapa perempuan lebih memilih memeluk pekerjaannya meski tak semenguntungkan itu.
“Sebenarnya kalau membicarakan job hugging, hal ini mungkin sudah dirasakan perempuan dari dulu karena memang pilihannya terbatas,” kata Hariati pada Magdalene (16/9).
Pernyataan ini selaras dengan temuan riset “Penggambaran Tubuh Perempuan dalam Iklan Lowongan Pekerjaan” (2017). Di sana dijelaskan lowongan pekerjaan masih memuat syarat yang mengobjektifikasi tubuh perempuan, seperti harus berpenampilan menarik, atau bertubuh kurus.
Selain itu, temuan lain dalam riset bertajuk “Bias Gender dalam Iklan Lowongan Pekerjaan” (2022), juga menemukan pekerjaan untuk perempuan masih terbatas pada bidang-bidang tertentu, seperti bisnis pelayanan. Enggak hanya itu, tuntutan kriteria terkait batas usia sampai status pernikahan juga jadi alasan sulitnya perempuan untuk mendapat opsi pekerjaan lain.
Fenomena ini pun tergambar dalam kisah Nisrina yang terjebak dalam job hugging. Ia bilang pilihannya untuk menjaga profesi saat ini dipengaruhi oleh kondisinya yang sudah menikah dan memiliki anak. Menurut Nisrina, tak banyak perusahaan yang mau menerima perempuan yang sudah berkeluarga.
“Kayaknya enggak banyak juga ya yang mau nerima perempuan beranak kayak gue gini. Susah lagi nyarinya. Bertahan aja udah, cicilan terlalu banyak,” ungkapya.
Hariati menambahkan, kondisi akan semakin parah apabila hal ini terjadi pada pekerja perempuan dengan pendapatan rendah. Pasalnya, mereka yang bertahan dengan gaji minim biasanya terjebak dalam situasi tanpa pilihan atas pekerjaan yang lebih baik.
Bagi mereka, pilihannya adalah bekerja atau tidak makan sama sekali. Hal ini bukan hanya membuat mereka terjebak dalam pengembangan diri yang nihil. Para pekerja, termasuk perempuan, bakal menerima semua konsekuensi kerja yang bisa merusak kesehatan mereka.
“Sebenarnya ini menunjukkan secara lintas kelas sosial, job hugging itu memberi dampak yang berbeda tapi sama-sama parah. Karena buat pekerja di kelas ekonomi yang lebih rendah, mungkin terlalu privilege gitu kalau ngomongin mental health atau pengembangan karier. Alasannya ya karena memang pilihannya kerja atau tidak makan sama sekali. Jadi mungkin banyak hak mereka yang bahkan enggak terpenuhi,” jelas Hariati.
Baca juga: Maaf, Usia 30 Dilarang Kerja: Ageisme yang Masih Hantui ‘Job Seeker’
Double Kill’ Pemerintah Egois, Lapangan Kerja Minim
Kesulitan mencari pekerjaan kini dirasakan hampir semua lapisan masyarakat. “Kondisi ini menggambarkan bagaimana kesulitan ekonomi kian dirasakan lebih meluas di semua lapisan masyarakat,” ujar Hariati.
Pernyataan itu diamini Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Ia menilai perekonomian Indonesia tengah terguncang dan berpotensi mengalami perlambatan pertumbuhan.
Terkait fenomena job hugging, Bhima menjelaskan hal ini erat kaitannya dengan makin berkurangnya ketersediaan lapangan kerja. Akar masalahnya, menurut dia, terletak pada keegoisan pemerintah yang lebih memilih mendorong investasi di industri padat modal dibandingkan padat karya. Dampaknya, penyerapan tenaga kerja pun menurun secara berkala.
“Sekarang ini investasi makin tidak berkualitas. Klaim serapan kerja per investasi yang masuk makin turun. Tahun 2015 setiap Rp1 triliun investasi menyerap 2.632 tenaga kerja, sedangkan semester 1 2025 cuma menyerap 1.273 orang tenaga kerja. Padahal banyak industri existing yang butuh suntikan modal, tapi karpet merah insentif diberikan ke investasi padat modal yang baru,” jelas Bhima (17/9).
Apa Solusinya?
Menurut Bhima, langkah cepat yang bisa diambil pemerintah adalah kembali melirik sektor padat karya untuk meningkatkan serapan tenaga kerja, agar industri yang masih bertahan tidak sampai gulung tikar.
“Sebetulnya bisa mulai dengan menyelamatkan industri existing dari gelombang penutupan. Jangan boros kasih insentif pajak ke sektor padat modal,” ucapnya.
Sebagai alternatif, Bhima menyebut masyarakat bisa mencoba berwirausaha dan menggerakkan perputaran ekonomi mandiri. Namun, ekosistem yang mendukung mutlak diperlukan, sehingga beban tidak sepenuhnya jatuh pada individu.
“Kalau fresh graduate mau jadi wirausaha silahkan, tapi ekosistemnya harus dibangun pemerintah. Soalnya banyak karyawan takut jadi wirausaha karena mitos wirausaha bisa dilakukan semua orang mulai banyak yang meragukan itu. Korupsi perizinan usaha itu juga harus diberantas, bukan cuma gimik digitalisasi aja,” terangnya.
Di sisi lain, bagi mereka yang masih merasa terjebak dalam pekerjaan sekarang, ada cara lain untuk tetap bertahan. Neuropsikolog Theo Tsaousides lewat tulisannya di Psychology Today menyarankan pekerja untuk membuat tujuan hidup di luar pekerjaan. Langkah ini, menurutnya, bisa membantu menemukan keseimbangan di tengah kebingungan karier. Meski bukan solusi utama, setidaknya pekerja dapat merasa lebih tenang di kondisi yang serba terimpit.
Read More