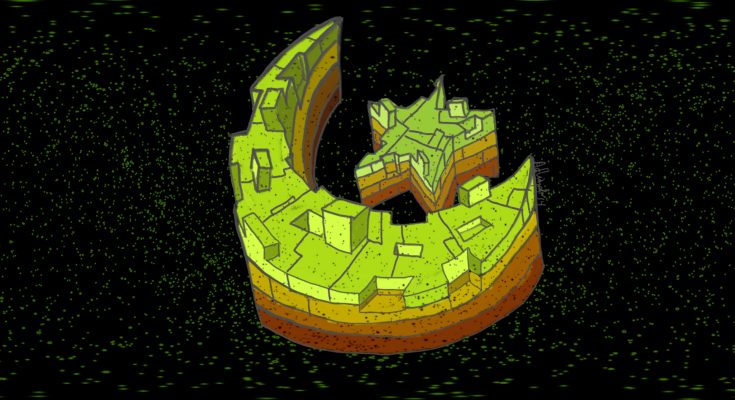Habis ‘Quiet Quitting’ Terbitlah ‘Loud Quitting’, Tren Baru yang Berbahaya
“Akhirnya Terbebas juga dari sini, fyuhhh!!” Begitulah bunyi Story Instagram “Cahya”, awal Desember lalu. Perempuan berusia 26 tahun itu sudah beberapa kali mengeluh dan bercerita kepadaku terkait beracunnya tempat ia bekerja.
Di sana, Cahya bekerja sebagai pegawai arsip yang menginput data-data klien bank. Ia mengeluh, perusahaan tak cukup transparan, memaksa ia bekerja hingga larut malam di akhir pekan tanpa upah layak, dan kontrak kerja yang sekadar tempelan karena kerap dilanggar perusahaan.
Mulanya, Cahya sendiri merasa ragu untuk berhenti kerja, setiap kali harus membayangkan sulitnya mendapat tempat kerja baru. Namun, karena semua keluhan Cahya terus direspons sepi oleh perusahaan, akhirnya ia menyerah.
Ia memutuskan mundur dan tak menyelesaikan tugas terakhirnya. Ia kesal dan kecewa setengah mati karena perusahaan dan atasan enggak bisa melindungi karyawan dan merugikannya.
Apa yang dialami oleh Cahya disebut dengan loud quitting. Istilah ini cukup populer akhir-akhir ini di lingkungan kerja. Menurut Forbes, loud quitting berpotensi lebih berbahaya dibandingkan quiet quitting. Lalu sebenarnya apa itu loud quitting?
Baca juga: Quiet Quitting: Kenapa Sedikit Kerja itu Bagus untukmu dan Bos
Perusahaan yang Toxic Menuntun Adanya Loud Quitting
Salah satu alasan Cahya mundur dari pekerjaannya adalah karena perusahaan dan atasan yang beracun (toksik). Mereka enggak pernah berterus terang tentang transparansi isi pekerjaan hingga mengabaikan kesejahteraan para pegawai.
Nihilnya transparansi itu kerap dikaitkan dengan istilah detoksifikasi budaya (cultural detox). Istilah tersebut datang dari dosen senior di Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Amerika Serikat, Sloan Donald Sull.
Dalam laporan Kompas, Sull mengatakan, detoksifikasi budaya mengacu pada proses mengidentifikasi dan mengatasi subkultur beracun dalam perusahan. Biasanya budaya perusahaan toksik berasal dari perpaduan kepemimpinan yang keras dan norma-norma sosial yang enggak inklusif, tanpa penghargaan, enggak etis, dan kejam. Makanya budaya ini menjadi pendorong kuat banyak pegawai yang stres, kelelahan dan memilih mencari tempat kerja lain.
Faktor-faktor inilah yang membuat loud quitting menjadi tak terhindarkan, sama seperti yang dilakukan Cahya. Enggak heran jika akhirnya ia ajeg mengungkapkan kekecewaan dan kekesalan ketika keluar dari tempat kerjanya. Ini adalah strateginya agar perusahaan bisa menyadari alasan mengapa ia mengundurkan diri.
Baca juga: Ratusan Kali Melamar Kerja, Ditolak karena Gendut
Berbahaya untuk Kedua Belah Pihak
Jika enggak segera dicarikan solusi, tindakan yang dilakukan oleh loud quitters ini akan berdampak negatif bagi perusahaan. Dilansir dari Forbes, para karyawan ini mungkin akan keluar tanpa pemberitahuan, membuat keributan di depan umum, mengunggah komentar daring yang menghasut, menolak melakukan tugas yang diberikan, melakukan tindakan yang mengganggu, serta berpotensi menyabotase. Perilaku ini dapat menjadi risiko besar dalam perusahaan dan enggak boleh diabaikan begitu saja oleh para atasan.
Sedangkan Gallup, perusahaan konsultasi manajemen kinerja asal Amerika Serikat mengatakan tindakan dari loud quitters juga berdampak pada reputasi, budaya serta produktivitas dalam perusahaan. Hal ini mencakup berkurangnya tingkat produktivitas karyawan, distraksi-distraksi, peningkatan turnover, hilangnya talenta terbaik, dan beban kerja meningkat bagi mereka yang tetap bekerja.
Lalu bagi karyawan yang memilih loud quitting, juga memiliki dampak buruk. Salah satunya, hubungan buruk dengan perusahaan sebelumnya akan merugikan ketika ingin mencari pekerjaan baru. Apalagi jika atasan memiliki pengaruh besar dan bisa memasukkan nama karyawan tersebut ke dalam blacklist-nya. Mereka disebut-sebut akan kesulitan untuk mendapat surat rekomendasi baik dari perusahaan tempat ia melakukan loud quitting.
Maka dari itu meski loud quitting cukup bisa membuat sebuah perusahaan berefleksi, namun alangkah baiknya kita masih ingin mencari pekerjaan untuk mempertimbangkan tindakan ini.
Baca juga: Ciri Lingkungan Kerja yang Sehat: Produktif dan Karyawan yang Sejahtera
Yang Bisa Dilakukan
Satu faktor penting yang menjadi banyaknya terjadi loud quitting karena lingkungan dan atasan yang toksik. Sull menawarkan beberapa cara yang bisa diambil oleh atasan untuk mulai memproses detoksifikasi budaya di perusahaan mereka.
Pertama, dengan menghitung detoksifikasi agar tetap menjadi agenda tim teratas. Contohnya, pemimpin bisa menjelaskan manfaat-manfaat apa saja dari lingkungan dan budaya kerja yang sehat, agar semua karyawan bisa mengetahuinya.
Kedua, melaporkan secara transparan kemajuan dan kekurangan pekerjaan juga berpotensi membentuk budaya kerja yang sehat.
Ketiga, pemimpin atau atasan perlu memberikan contoh baik yang mereka harapkan dari para karyawan.
Keempat, pemimpin sama sekali enggak boleh mengabaikan saran dan pesan yang dibuat oleh karyawan. Ketika mereka ingin menilai kinerja budaya perusahaan.
Selain itu yang paling penting adalah pemimpin harus bisa memprioritaskan kesejahteraan para pekerjanya. Pun, mereka harus bisa menunjukkan apresiasi bagi siapa saja yang melakukan pekerjaan dengan baik. Dengan ini, karyawan akan merasa dihargai dan diakui kinerjanya. Hal ini pun akan membuat baik perusahaan dan para karyawan bisa menciptakan lingkungan kerja yang sehat bersama-sama.
Read More