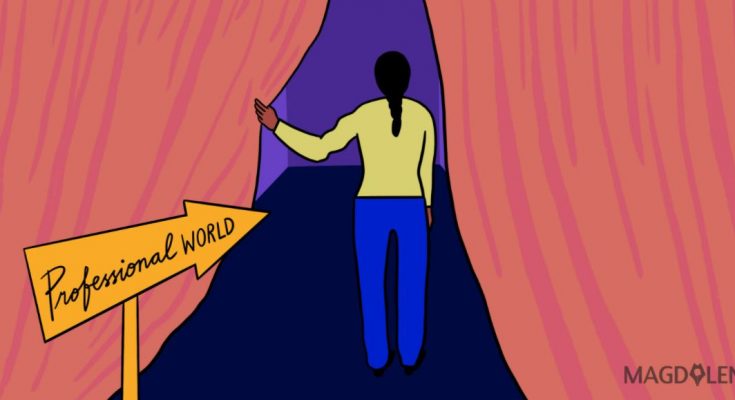
Selamat Tinggal Jepang, Tanah Para Pejuang Korporat: Kisah Seorang Ibu Pekerja
Pada usia 30, saya menemukan bahwa saya hamil. Saya telah membayangkan momen ini sepanjang hidup saya, bahwa saya akan menangis gembira. Tetapi yang membuat saya terkejut, saya malah menangis kecewa. Selama kunjungan pertama saya ke dokter kandungan dengan suami saya, saya terus menghela nafas, “Apakah terlalu dini untuk punya anak?”
Respons dari suami saya, yang sebetulnya jarang marah, sungguh tidak terlupakan. “Jangan pernah bilang begitu di depan anakmu!” dia menegaskan dengan nada keras, seolah-olah anak kita yang belum lahir sudah ada di depannya.
Karena selalu ingin bekerja di negara berkembang, saya mengejar karier di bidang kerja sama internasional. Saya terbang keliling Afrika, Timur Tengah, dan Asia, berdamai dengan posisi asisten saya, mempersiapkan kontrak untuk ditandatangani oleh bos laki-laki paruh baya saya. Tetapi ketika saya mendapatkan pengalaman yang cukup setelah tujuh tahun bekerja, kehamilan saya datang sebagai takdir yang tidak terduga.
Saya dulu percaya kesetaraan gender ada di Jepang, sampai saya melahirkan anak pertama saya.
Saya mengambil cuti melahirkan satu tahun penuh, dan menjelang akhir masa cuti, saya disela oleh sebuah panggilan telepon saat sedang berada di studio foto untuk mengambil foto bayi saya. Itu dari manajer bagian yang belum pernah berkomunikasi dengan saya sebelumnya. Dengan nada sangat formal, dia memberi tahu saya bahwa saya akan mulai bekerja di divisi baru mulai minggu depan. Pekerjaan saya di divisi baru ini tidak memerlukan perjalanan bisnis ke luar negeri.
Hati saya langsung mencelos. Saya bertanya mengapa, dia menjawab, “Saya hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah keputusan HRD. Ini adalah rotasi, jadi Anda akan berada di sana selama beberapa tahun ke depan.”
Ibu Pekerja dan Diskriminasi Gender

Setelah saya kembali bekerja, saya terus-menerus mendengar ungkapan, “Karena Yamamoto-san adalah seorang ibu.” Awalnya mungkin terdengar bijaksana, tapi saya kesal dengan pertimbangan yang berlebihan untuk status baru saya yang bahkan tidak pernah saya inginkan sebelumnya. Saya mencoba memberi tahu bos saya beberapa kali, tetapi sepertinya saya berbicara dalam bahasa yang tidak dapat dipahami oleh laki-laki Jepang.
Baca Juga: Akademisi Perempuan Tanggung Beban Lebih Berat Selama Pandemi
Saya menunggu dengan sabar dan menahan ketidaknyamanan selama bertahun-tahun, sementara saya menyaksikan rekan laki-laki saya naik jabatan menjadi manajer proyek atau bahkan manajer bagian. Namun, subjek pekerjaan atau promosi di luar negeri terus menghindar dari saya. Ada beberapa perempuan yang dipromosikan ke posisi manajerial, namun semuanya perempuan lajang atau perempuan tanpa anak. Bagi saya, mereka diperlakukan sebagai perempuan yang bisa bekerja seperti laki-laki.
Sementara perempuan berfokus pada pengasuhan anak, laki-laki bekerja lembur, sering kali lewat tengah malam, sebagai pejuang korporat yang mendapat manfaat dari pengorbanan perempuan. Masyarakat Jepang beroperasi berdasarkan asumsi bahwa perempuan akan membesarkan anak-anaknya sendirian.
Jepang memberlakukan cuti hamil satu tahun yang dibayar, yang dibandingkan dengan negara-negara kaya lainnya, cukup progresif. Tetapi apakah ini membuat Jepang menjadi negara yang hebat bagi perempuan? Apa yang dilakukan laki-laki sementara perempuan mendedikasikan diri pada pengasuhan anak selama setahun penuh? Cuti ayah pada saat itu hanya mencapai 1 persen, dan kemudian hanya meningkat menjadi 6 persen.
Dengan kata lain, sementara perempuan berfokus pada pengasuhan anak, laki-laki bekerja lembur, sering kali lewat tengah malam, sebagai pejuang korporat yang mendapat manfaat dari pengorbanan perempuan. Masyarakat Jepang beroperasi berdasarkan asumsi bahwa ibu pekerja akan membesarkan anak-anaknya sendirian tanpa bantuan pasangan.
Kata “ikumen” menjadi fenomena di Jepang beberapa waktu lalu. Istilah yang saya sangat benci itu, yang secara harfiah berarti “seorang laki-laki yang membesarkan seorang anak”, digunakan untuk memuji seorang laki-laki yang secara aktif berpartisipasi dalam pengasuhan anak. Perempuan tidak diberi pilihan untuk “berpartisipasi” atau “tidak berpartisipasi” dalam hal mengasuh anak, sedangkan laki-laki dipuji dengan “berpartisipasi” dalam membesarkan anak mereka sendiri. Setiap kali saya mendengar kata ini, saya merinding.
Ketimpangan Gender di Tempat Kerja

Ketika perusahaan memindahkan saya ke divisi yang sama dengan yang beberapa tahun yang lalu tempati untuk kedua kalinya, saya memutuskan bahwa inilah sudah saatnya untuk pergi. Setelah 17 tahun bersama organisasi tersebut, saya merasa sudah cukup. Saya putus asa mencari cara untuk bekerja di luar negeri. Ada posisi penempatan di Kedutaan Jepang di luar negeri, tetapi ketika saya bertanya kepada manajer SDM untuk lowongan apa saja, dia menjawab, “Posisi itu untuk orang yang lebih muda.”
Baca Juga: Stereotip Gender dalam Periklanan Indonesia dan Global
Betapa bodohnya saya untuk percaya bahwa seorang ibu pekerja memiliki kesempatan yang sama di Jepang. Sementara saya terlalu sibuk membesarkan anak-anak saya, rambut acak-acakan dan sebagainya, nilai pasar saya seharusnya berada pada titik tertinggi. Tetapi ketika saya akhirnya kembali ke realitas pada akhir usia tiga puluhan, saya adalah seorang karyawan biasa yang tidak dapat diberikan pekerjaan yang substansial.
Saya berharap seseorang telah memberi tahu saya tentang keberadaan jalur menjadi seorang ibu pekerja yang tak terucapkan, dan memperingatkan saya untuk tidak pernah masuk ke penjara bawah tanah ini ketika saya masih muda dengan semua mimpi ambisius. Saya merasa hancur lebur.
Saya kemudian menemukan lowongan pekerjaan di sebuah organisasi internasional yang berkantor pusat di Jakarta. Suami saya tampak agak bingung pada awalnya. “Apa yang akan saya lakukan di Jakarta? Apa yang akan kita lakukan dengan rumah kita di Tokyo? Apa yang akan terjadi dengan kucing kita?”
Perempuan tidak diberi pilihan untuk “berpartisipasi” atau “tidak berpartisipasi” dalam hal mengasuh anak, sedangkan laki-laki dipuji dengan “berpartisipasi” dalam membesarkan anak mereka sendiri.
Saya terkekeh dan mengatakan kepadanya bahwa saya mungkin tidak akan mendapatkan pekerjaan itu, sambil mengisi formulir aplikasi. Kemudian, saya diberitahu bahwa aplikasi saya lulus penyaringan, dan proses lamaran saya berlanjut ke wawancara video. Setelah pertanyaan-pertanyaan umum, di akhir wawancara, satu-satunya laki-laki Jepang di panel melontarkan pertanyaan yang tidak terduga: “Mengapa Anda ingin berganti pekerjaan di luar negeri sekarang, ketika Anda memiliki anak kecil?”
Baca Juga: Bentuk Diskriminasi Gender di Tempat Kerja dan Cara Mengatasinya
Jangan ini lagi, pikir saya. Suara saya bergetar karena marah, karena tahu dia tidak akan pernah menanyakan pertanyaan yang sama jika aku laki-laki. “Di Jepang, ada stereotip bahwa perempuan harus bertindak dengan cara tertentu. Saya melamar posisi untuk mendobrak batasan itu agar perempuan yang lebih muda mengikuti jejak saya,” ujar saya.
Saya seharusnya tidak mengatakan itu, saya mungkin terdengar terlalu bersemangat. Tapi ketika saya larut dalam penyesalan, ada panggilan internasional dari Indonesia: “Kami ingin memberi Anda penawaran kerja. Kapan Anda bisa bergabung?”
Ibu Pekerja dan Beban Ganda

Masih tidak percaya, saya segera menjalani prosedur pengunduran diri, menjual rumah saya, dan merencanakan perpindahan besar tiga bulan kemudian. Suami saya, yang tidak mengira saya akan diterima, memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya setelah banyak konflik.
Orang tua saya, yang telah lama tinggal di Amerika Serikat dan Eropa, tanpa ragu memberi selamat kepada saya. ” Jakarta lebih dekat dari Jepang daripada Eropa. Kami berharap dapat berkeliling Asia Tenggara saat kamu berada di sana.”
Tapi ibu mertua saya yang menghalangi kami. Dia lulusan universitas nasional dan menjadi guru sekolah dasar pada tahun 1970-an. Dia terus bekerja sambil membesarkan kedua anaknya hingga pensiun dini di usia 50-an. Saya terlalu optimis untuk berpikir bahwa dia akan mendukung keputusan kami untuk pergi ke Jakarta, jadi reaksinya tidak terduga.
Baca Juga: Apakah Aturan Kenaikan Upah Minimum Sudah Efektif Lindungi Pekerja?
Ibu mertua saya tidak ingin membiarkan putranya, lulusan universitas yang meninggalkan posisi karyawan tetapnya untuk ikut bersama istri dan anak-anaknya. Dia menyebutkan berbagai alasan lain, seperti anak-anak yang kehilangan pendidikan di Jepang dan masalah keamanan di Jakarta, tetapi itu semua bermuara pada reputasi putra sulungnya yang meninggalkan pekerjaannya karena mengikuti istrinya.
Ada ungkapan dalam bahasa Jepang yang menghargai laki-laki dan meremehkan perempuan yang berasal dari kitab Konfusianisme. Meski kami diajari bahwa laki-laki dan perempuan sama selama beberapa dekade, perempuan juga masih memegang keyakinan ini, seperti ibu mertua saya.
Meskipun demikian, suami saya meyakinkan saya bahwa kami sudah dewasa dan penolakan ibunya seharusnya tidak memengaruhi keputusan kami. Kami menulis surat untuk membujuk ibu mertua saya. Bahwa meskipun ia akan meninggalkan pekerjaannya di Jepang, kariernya selama lebih dari sepuluh tahun di bidang penjualan pasti berguna untuk mendapatkan pekerjaan di salah satu dari 1.500 perusahaan Jepang di Jakarta. Usaha kami berakhir sia-sia, karena dia masih tidak setuju. Tetapi setidaknya dia mengerti bahwa keputusan kami tidak akan berubah, jadi dia membalas bahwa dia tidak akan lagi mencoba meyakinkan kami.
Peran Aktif Perempuan di Asia Tenggara

Sudah hampir dua tahun sejak saya datang ke Jakarta. Peran aktif perempuan Asia Tenggara di tempat kerja sangat luar biasa. Selain itu, seorang perempuan tidak perlu membesarkan anak sendirian di sini. Saya sangat berterima kasih kepada pengasuh anak saya yang tinggal bersama kami dan seorang pekerja rumah tangga yang membantu saya dengan perawatan anak dan pekerjaan rumah.
Saya telah berjuang selama ini untuk menangani perawatan anak dan pekerjaan sebagai ibu pekerja, yang tidak mungkin dilakukan di Jepang. Untuk pertama kalinya dalam satu dekade, saya bisa fokus pada pekerjaan saya tanpa merasa bersalah. Saya berterima kasih kepada suami saya, yang menemukan pekerjaan di sebuah perusahaan Jepang setelah menjadi bapak rumah tangga selama hampir satu tahun.
Baca Juga: 5 Rekomendasi Novel Terbaik Untuk Perempuan Pekerja
Terkadang saya bertanya-tanya tentang diri saya di dunia paralel: Jika saya memutuskan untuk tinggal di Jepang sebagai seorang ibu pekerja, apakah saya akan menghancurkan diri saya sendiri? Saya hanya bisa mengatakan bahwa perubahan karier pertama saya pada usia 40 tahun adalah lompatan besar yang ternyata tidak terlalu buruk. Nyatanya, saya berusaha untuk tidak merasa terlalu nyaman di sini, atau saya tidak akan pernah bisa bekerja di Jepang lagi.
Sedangkan untuk ibu mertua saya, kami memberinya tablet sebagai hadiah perpisahan, alat yang belum pernah dia gunakan sebelumnya dalam hidupnya. Pada awalnya, dia bahkan enggan untuk memulai memakai gawai itu, menyalahkan penglihatannya yang sudah memburuk. Tapi saya terus mengirimkan foto cucunya dan berkomunikasi melalui LINE lebih sering daripada yang pernah kami lakukan di Jepang. Setiap kali dia melihat foto-foto kami menikmati hidup kami di sini, saya bisa merasakan hatinya semakin terbuka.
Artikel ini diterjemahkan oleh Jasmine Floretta V.D. dari versi aslinya dalam bahasa Inggris yang dimuat Magdalene.co.
Haru adalah perempuan Jepang yang lahir di Eropa, dibesarkan di AS dan sekarang bekerja di sebuah organisasi internasional di Jakarta. Dia adalah perempuan yang pendiam, pemalu dan sederhana dengan dua anak perempuan, satu suami dan kekuatan super untuk berbicara dengan kucing.
Read More
