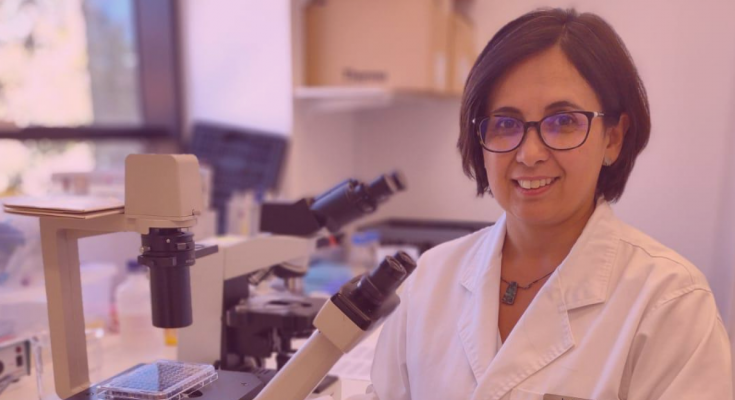Ketika kita membaca daftar jurnalis ternama atau bersejarah dari mancanegara di berbagai artikel atau buku, biasanya hanya sedikit jurnalis perempuan yang disebutkan. Padahal, tidak sedikit jurnalis perempuan yang berkontribusi terhadap perkembangan dunia jurnalistik di seluruh dunia. Usaha mereka untuk membantu kelompok minoritas dan memperjuangkan kebebasan berpendapat dapat kita telusuri jejaknya dari abad ke abad.
Dalam dunia jurnalistik yang patriarkal sejak awal perkembangannya, perempuan mesti berusaha keras untuk mencari ruang agar bisa bersuara dan didengar. Sering kali, mereka yang memperoleh posisi strategis di bidang jurnalistik mendapatkan perlawanan keras, pelecehan, hingga penindasan. Para jurnalis perempuan pun kadang dipandang tidak cukup mampu untuk meliput berita-berita “berat” seperti politik dan perang.
Namun, setelah melalui perjuangan di berbagai belahan dunia, perlahan jurnalis perempuan membuktikan bahwa peran mereka terlalu besar dan penting untuk dikucilkan.
Berikut ini kami rangkum sejumlah nama jurnalis perempuan terkemuka dunia yang perlu kamu ketahui.
1. Anne-Marguerite Petit du Noyer
Perempuan asal Perancis ini merupakan salah satu jurnalis perempuan tersohor pada abad ke-18. Berbeda dari kebanyakan jurnalis perempuan lainnya pada masa itu, du Noyer tidak berasal dari sektor percetakan.
Lahir dalam keluarga Protestan pada tahun 1663, du Noyer menjadi seorang Katolik ketika kaum Huguenots (Protestan) dipersekusi. Namun, pada akhirnya ia kembali menjadi seorang Protestan dan diusir dari Perancis karena hal tersebut.
Ia mulai menulis dalam surat kabar mingguan Quintessence of News mengenai Perjanjian Utrecht antara Inggris dan Spanyol (1713-1715) yang mengakhiri perang Spanyol. Hasil laporannya sangat diapresiasi dan sejak itu, ia dikenal oleh masyarakat umum.
Sosok dan sepak terjang du Noyer yang terukir dalam sejarah menjadi faktor yang sangat berpengaruh bagi perempuan lainnya dalam menulis tentang kontroversi-kontroversi penting di sekitar mereka. Laporan yang mereka kirim ke surat kabar pada tahun-tahun berikutnya tidak lepas dari semangat du Noyer dalam mengungkap skandal yang patut untuk diketahui masyarakat setempat.
Baca juga: 7 Tokoh Perempuan yang Berperan dalam Proklamasi Kemerdekaan
2. Jurnalis Perempuan Hebat: Maria Ilnicka
Maria Ilnicka adalah seorang penyair, novelis, penerjemah, dan juga jurnalis asal Polandia. Ia dikenal karena partisipasinya dalam pemberontakan melawan Kekaisaran Rusia yang menduduki negaranya pada awal 1860an.
Maria Ilnicka bertindak sebagai juru arsip Polish National Government selama Pemberontakan Januari yang dilakukan Polandia pada tahun 1863. Dua tahun kemudian, ia menjadi pemimpin redaksi jurnal mingguan untuk perempuan bernama Bluszczu.
Ia dikenal sebagai sosok yang mendukung pendidikan untuk seluruh rakyat. Setelah dirinya, jurnalis-jurnalis perempuan lain bermunculan dan meneruskan perjuangannya tersebut hingga saat ini.
3. Jurnalis Perempuan Jepang Pertama: Hani Motoko
Berbicara mengenai pengaruh dan upaya para jurnalis dalam bidang pendidikan, pengaruh Hani Motoko juga tidak dapat dilewatkan. Hani Motoko adalah jurnalis perempuan pertama di Jepang dan juga pelopor pengembangan pendidikan untuk perempuan negata itu. Kariernya berlangsung selama lebih dari setengah abad, dari akhir masa Kekaisaran Meiji hingga pertengahan abad ke-20.
Pendidikan untuk perempuan masih merupakan subjek kontroversial pada Zaman Meiji. Pandangan pemerintahan terhadap perempuan pada masa itu dinyatakan dalam slogan “istri yang baik, ibu yang bijak”. Edukasi yang diperoleh perempuan hanya terbatas dalam aspek “kewanitaan” dan persiapan untuk menikah, berbeda dengan laki-laki yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin dan kepala rumah tangga.
Motoko meniti karier dari penyunting naskah hingga reporter dan penulis editorial Hochi Shinbun pada tahun 1897, di saat surat kabar lain hanya membolehkan perempuan menulis perihal rumah tangga. Melihat sekolah negeri terus mengajarkan perempuan untuk menjadi sosok yang tunduk dan patuh, ia bersama sejumlah pendidik lain pun mendirikan Jiyu Gakuen, sebuahsekolah khusus perempuan.
Di sekolah tersebut, Hani Motoko dan kawan-kawan mengajarkan individualisme bagi perempuan dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pengurus finansial dalam keluarga. Nilai kebebasan, harga diri, dan kemerdekaan terus digaungkan Motoko di sepanjang kariernya sebagai jurnalis dan pengajar.
4. Jovita Idár
Jurnalis perempuan yang tercatat dalam sejarah tidak hanya memperjuangkan hak-hak kaum perempuan semata. Jovita Idár adalah jurnalis Meksiko-Amerika yang dikenal karena jerih payahnya dalam melindungi hak-hak kaum minoritas.
Baca Juga: Memperkenalkan Kesetaraan Gender Mulai dari Buku-buku Teks Anak
Lahir di Laredo, Texas, pada tahun 1885, Idár mulai meniti karier di surat kabar milik ayahnya, La Crónica, yang mengecam dan melawan penganiayaan terhadap orang Meksiko-Amerika. Ia pun kerap menulis tentang rasisme di Meksiko dan turut mendukung revolusi yang mulai berkembang di sana. Idár juga menjadi presiden organisasi perempuan Meksiko bernama La Liga Femenil Mexicanista yang menawarkan pendidikan gratis kepada anak-anak Meksiko.
Selama berlangsungnya Revolusi Meksiko pada tahun 1913, ia pergi ke Meksiko untuk merawat korban luka-luka. Tetapi, Idár kembali ke AS pada tahun berikutnya untuk mengambil alih La Crónica dan terus berkampanye mengangkat isu kehidupan kaum Meksiko-Amerika yang buruk. Idár pun tidak henti-hentinya mengadvokasikan hak-hak perempuan, terutama ketika ia menduduki posisi dalam Partai Demokrat di Texas.
5. Peggy Hull
Peggy Hull sebenarnya adalah nama pena yang singkat milik Henrietta Eleanor Goodnough Deuell, jurnalis perempuan pertama yang diakreditasi secara resmi oleh Departemen Perang Amerika Serikat.
Awalnya, Hull menulis di berbagai surat kabar, seperti Honolulu Star di Hawaii, Cleveland Plain Dealer di Ohio, atau Junction City Daily di Kansas, tempat ia tumbuh besar. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai memasuki ranah berita militer. Ia terjun meliput Perang Dunia I dan II.
Dalam meliput kedua perang tersebut, Hull melintasi berbagai kontinen dan negara dari Perancis hingga Siberia. Kariernya sebagai jurnalis perang dan tulisan yang ia hasilkan lantas membuatnya memperoleh penghargaan Angkatan Laut Amerika Serikat. Kesuksesannya pun menunjukkan bahwa perempuan mampu meliput topik peperangan yang sering dianggap tidak layak bagi mereka.
6. Minna Lewinson
Tumbuh dan besar di New York City, Minna Lewinson mengenyam pendidikan jurnalisme di Barnard College, Columbia University. Dari situ, ia bekerja sebagai reporter di berbagai publikasi seperti Daily Investment News dan Women’s Wear Daily. Ia juga merupakan jurnalis perempuan pertama yang direkrut oleh The Wall Street Journal pada tahun 1918.
Lewinson adalah jurnalis perempuan pertama yang memenangi Penghargaan Pulitzer untuk jurnalisme pada tahun 1918, bersama Henry Beetle Hough. Penghargaan tersebut mereka terima setelah menulis sejarah surat kabar.
Lewinson pun menjadi pembuka gerbang untuk jurnalis-jurnalis perempuan selanjutnya untuk memenangi penghargaan ini. Meski begitu, kategori sejarah surat kabar hanya pernah diberikan kepada Lewinson dan sejak itu tidak pernah ada lagi.
7. Munira Thabit
Munira Thabit adalah perempuan asal Mesir dan merupakan salah satu jurnalis perempuan yang merintis perjuangan meraih kesetaraan gender. Thabit mengawali kariernya sebagai pengacara di Mesir dan menjadi perempuan pertama di ranah tersebut. Namun, karena banyaknya halangan terhadap partisipasi perempuan di ranah pengadilan Mesir, ia berpindah haluan ke jurnalisme.
Thabit selalu mengutarakan bahwa perempuan berhak untuk memperoleh kesetaraan di ruang kerja, pendidikan, bahkan lingkup keluarga. Ia menerbitkan surat kabar mingguan bernama al-Amal pada tahun 1926 dengan slogan “Surat Kabar yang Melindungi Hak Politik Perempuan”. Meskipun ia mendapat perlawanan dari para tokoh agama dan aparat pemerintah, Thabit tidak berhenti dan terus menulis beragam artikel mengenai hak-hak perempuan.
Di tingkat internasional, Munira Thabit telah dipandang sebagai jurnalis terbaik Mesir pada masanya. Ia menjadi perwakilan Mesir di konferensi jurnalisme internasional di Jerman, partisipan di Egyptian Feminist Union (EFU), dan turut mendirikan Perserikatan Jurnalis Mesir.
Memoarnya yang berjudul A Revolution in the Ivory Tower: My Memories of Twenty Years of Struggle for Women’s Political Rights berisi komentar-komentar politik yang telah ia tulis di sepanjang kariernya.
Baca juga: Rekam Jejak Jurnalis Perempuan Indonesia dan Tantangan yang Harus Mereka Hadapi
8. Frances FitzGerald
Tulisan jurnalis lepas Frances FitzGerald mengenai Perang Vietnam adalah salah satu bukti perempuan bisa menelurkan karya yang diakui dunia internasional. Berkat karya non-fiksinya yang bertajuk Fire in the Lake: The Vietnamese and the Americans in Vietnam, FitzGerald diganjar Penghargaan Pulitzer pada 1973. Tulisannya itu disebut sebagai salah satu analisis terbaik mengenai keadaan di Vietnam.
Tumbuh besar di New York City, FitzGerald lulus dengan magna cum laude dari Radcliffe College pada tahun 1962. Ia memulai karier jurnalistiknya di majalah New York Herald Tribune sebelum akhirnya pergi ke Vietnam sebagai jurnalis lepas dan menghabiskan waktu selama 16 bulan di sana.
FitzGerald pun mempelajari budaya serta sejarah Vietnam dan Cina sedalam mungkin. Jika para jurnalis laki-laki melaporkan aksi eksplosif peperangan yang sedang terjadi di sana, ia lebih berfokus kepada dampak perang tersebut terhadap kondisi politik dan masyarakat Vietnam Selatan.
FitzGerald dianggap berhasil memandang perang dengan perspektif alternatif telah menunjukkan pentingnya peran perempuan di berbagai ranah jurnalistik.
9. Christiane Amanpour
Christiane Amanpour adalah jurnalis Inggris yang merupakan salah satu koresponden perang ternama di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Pemberitaannya dapat kita temui di program-program CNN, ABC, dan PBS.
Amanpour dibesarkan di Tehran hingga umur 11 tahun sebelum kembali ke Inggris, tempat kelahirannya. Ia melanjutkan pendidikannya di University of Rhode Island, Amerika Serikat, dan setelah lulus pada tahun 1983, ia memperoleh pekerjaan pertamanya di CNN sebagai asisten untuk ruang redaksi berita internasional.
Ketika Perang Teluk Persia pecah pada tahun 1990, Amanpour mulai dikenal sebagai reporter yang meliput konflik dengan baik. Ia disebut dapat menarasikan kebiadaban perang dan kejinya suatu konflik ke khalayak umum. Amanpour meliput invasi Irak ke Kuwait, kedatangan Amerika Serikat, dan setelahnya berlanjut ke pemberontakan Kurdi.
Begitu andalnya Amanpour meliput di medan perang, hingga kini namanya dipakai dalam program serial CNN dan PBS sebagai pembawa acara di kedua saluran TV tersebut.
10. Jurnalis Perempuan Asal Filipina: Maria Ressa
Nama dan profil Maria Ressa muncul pada majalah TIME edisi Person of the Year tahun 2018. Ia disebut sebagai salah satu jurnalis yang tidak henti melawan berita sesat atau hoaks. Upaya Ressa dalam memperjuangkan kebebasan pers pun bukan kisah yang asing lagi.
Maria Ressa merupakan jurnalis Filipina yang telah meniti kariernya di berbagai belahan dunia: menjadi reporter investigasi Asia untuk CNN, pemimpin divisi berita di ABS-CBN, menulis untuk The Wall Street Journal, dan mengajar di Princeton University. Ia kemudian mendirikan bisa dibilang adalah Rappler, media berita online yang didirikannya pada tahun 2012.
Di bawah kepemimpinannya, kritik terhadap Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengenai kebijakan-kebijakannya mengisi laman media berita tersebut. Karena sosoknya yang vokal tersebut, Ressa bahkan sempat beberapa kali ditangkap.
Rappler kini telah meraih berbagai macam penghargaan dan menjadi salah satu portal berita terbesar di Filipina.
11. Jurnalis Perempuan Indonesia: Roehana Koeddoes
Roehana Koeddoes Lahir di Sumatra Barat pada tanggal 20 Desember 1884, Roehana Koeddoes merupakan figur seorang pejuang intelektual yang dipanggil sebagai Wartawati Pertama Indonesia dan pelopor Pers Indonesia.
Baca Juga: 4 Pahlawan Perempuan dari Jawa Barat adalah Tokoh Feminisme
Hidup di era yang sama dengan R.A Kartini di mana pada waktu itu kaum perempuan masih tidak bisa mendapatkan pendidikan formal, Roehana beruntung karena punya sosok ayah yang mau mengajarinya banyak hal dari ia kecil, terutama dalam soal membaca, menulis, dan berbahasa.
Sejak ia kecil sudah banyak membaca buku-buku, Roehana tumbuh dewasa dengan pemikiran yang semakin hari semakin tajam, apalagi mengenai politik dan sadar pada isu-isu emansipasi, satu hal yang mendapat tentangan keras tidak cuma dari pemerintah Belanda, tapi juga kaidah agama serta budaya setempat.
Merasa tidak puas cuma berhasil membuat sekolah keterampilan buat perempuan Indonesia, Roehana pun membuat surat kabar bernama Sunting Melayu pada tanggal 10 Juli 1912, yang faktanya ternyata surat kabar yang ia bangun merupakan surat kabar pertama di Indonesia yang dipimpin, dijalankan, dan ditujukan untuk kaum perempuan.
Dengan isu nasionalisme dan emansipasi perempuan dalam soal pendidikan, Roehana mengemban tugas sebagai pemimpin redaksi yang ikut dibantu oleh sosok Zubaidah Ratna Djuwita. Tak cuma jadi tempat untuk berpendapat para perempuan di Sumatra Barat, Sunting Melayu yang terbit seminggu sekali dan bertahan terbit sampai 9 tahun juga menerima tulisan dari wilayah-wilayah lain di Indonesia.
Baca Juga: 10 Nama Pahlawan Perempuan Indonesia yang Harus Kalian Ketahui
Selain Sunting Melayu, Roehana juga pernah menjadi pemimpin surat kabar Perempuan Bergerak di Medan serta surat kabar Radio dan Cahaya Sumatera di Padang. Karena jasanya yang besar dalam dunia jurnalistik, edukasi, dan politik, Roehana yang wafat pada tanggal 17 Agustus 1972 di Jakarta pun dianugerahi Bintang Jasa Utama oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2007 yang lalu.
Kisah-kisah sepuluh jurnalis perempuan ini tentu tidak cukup untuk menggambarkan kiprah dan prestasi jurnalis perempuan di seluruh dunia. Namun, daftar ini dapat menjadi awal kita untuk menghargai perjuangan perempuan di dunia jurnalistik!
Read More