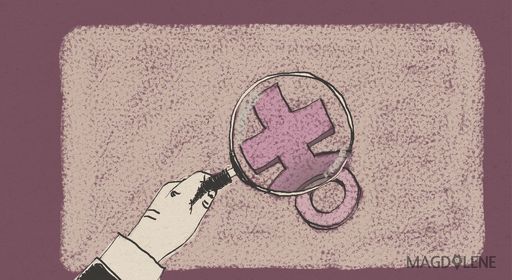Penulis: Bini Fitriani
Jumlah perempuan kepala daerah dan anggota DPR adalah hal krusial untuk menciptakan kultur pengambilan kebijakan publik yang lebih sensitif terhadap kepentingan perempuan. Urgensi untuk mewujudkan peningkatan jumlah ini memicu lahirnya peraturan dalam Undang-Undang (UU) No. 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mempersyaratkan sekurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik.
Namun sayangnya, banyak kendala dalam meningkatkan peran perempuan dalam politik di sini. Salah satunya, sekalipun hampir semua partai politik sudah mengikuti syarat kuota 30 persen untuk perempuan, masih sedikit jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR. Hal ini tidak lepas dari masih minimnya penempatan kader perempuan di posisi-posisi strategis dalam partai.
Di lain sisi, affirmative action berupa persyaratan kuota bagi perempuan dalam partai masih mengundang polemik. Ada pihak yang mengkritik bahwa keterwakilan perempuan dalam politik sebagai pengambil kebijakan publik belum tentu benar-benar berpihak pada perempuan. Mereka menganggap, sering kali politisi perempuan tak ubahnya dengan politisi laki-laki yang berideologi patriarki dan melanggengkan ketidaksertaraan gender.
Baca juga:Politik Afirmasi dan Permasalahannya Bagi Perempuan
Kontribusi perempuan kepala daerah
Data kuantitatif dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 dan Peraturan Mentreri Dalam Negerti (PERMENDAGRI) tahun 2015 menunjukkan bahwa jumlah perempuan di lembaga pengambil kebijakan publik masih jauh dari yang diharapkan.
Pada tingkat legislatif, kuota 30 persen yang diatur pada UU No. 8/2012 tidak pernah tercapai.
Pada tingkat eksekutif, jumlah perempuan kepala daerah masih rendah. Dari 416 kepala daerah, hanya 35 orang (8,7 persen) perempuan terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015; 13 orang (5,9 persen) pada Pilkada 2017; dan 101 orang (8,85 persen) perempuan dari total 1140 calon kepala daerah pada Pilkada 2018. Untuk posisi kepala desa, hanya empat persen perempuan menduduki posisi tersebut dari seluruh desa di Indonesia.
Dari segi kontribusi para perempuan pengambil kebijakan ini, masih ada catatan buruk yang mesti diperbaiki di kemudian hari. Data kualitatif dari lembaga-lembaga pemerhati isu politik seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Cakra Wikara Indonesia menunjukkan hal ini. Mereka mencatat, jumlah perempuan yang berada pada lembaga-lembaga pengambil kebijakan publik belum banyak berkontribusi mengatasi isu ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Padahal, isu-isu tersebut diharapkan menjadi prioritas para politisi atau pemimpin perempuan.
“Kehadiran perempuan seharusnya berkontribusi melalui visi, misi, dan program yang membawa suara perempuan dan anak. Namun, riset Perludem tahun 2015 menunjukkan bahwa tidak semua perempuan kandidat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah membuat perencanaan program mengenai perempuan dan anak, atau isu-isu kesetaraan dan keadilan gender,” papar Titi Anggraini, anggota dewan pembina Perludem kepada Magdalene.
“Hanya 17 persen dari keseluruhan kandidat yang melakukan hal tersebut,” imbuh Titi.
Lebih lanjut Titi menyatakan, berdasarkan riset lembaganya tahun 2014, partai politik cenderung “asal comot” kandidat perempuan untuk memenuhi kuota 30 persen. Ini dipengaruhi oleh ketiadaan upaya partai untuk melakukan kaderisasi secara terus menerus kepada semua anggotanya, terlebih perempuan, sehingga kaderisasi hanya dilakukan menjelang Pilkada saja. Keterbatasan upaya partai melakukan kaderisasi dipengaruhi oleh besarnya dana yang dibutuhkan untuk hal tersebut. Akibatnya, kualitas anggota partai perempuan pun cenderung jalan di tempat.
“Public funding dapat menjadi salah satu solusi, yaitu melalui penguatan alokasi dana negara untuk partai,” saran Titi.
Menurut Ann Phillips dalam bukunya, The Politics of Presence (1998) mengenai prinsip keterwakilan politik, politik bagi perempuan idealnya bukan hanya dimaknai sebagai pertarungan ide dan gagasan. Ini juga diartikan sebagai sebuah kehadiran yang memberikan makna dalam dunia politik (politics of presence). Caranya, lewat perwujudan sikap responsif dan akuntabel dalam menanggapi isu-isu yang berdampak negatif terhadap demokrasi. Dengan demikian, keterwakilan perempuan dalam dunia politik seharusnya bukan sekadar jumlah (beyond numbers).
Budaya patriarkal hambat perempuan kepala daerah
Budaya maskulin yang masih mendominasi birokrasi dan partai-partai di Indonesia adalah satu hal yang mempengaruhi minimnya jumlah perempuan kepala daerah dan anggota wakil rakyat. Salah satu akibat dari berlakunya budaya ini ialah pandangan sebelah mata terhadap perempuan pengambil kebijakan, terlepas dari apakah perempuan tersebut berkapasitas atau tidak.
Ini bisa dilihat dari contoh pemimpin perempuan seperti Megawati Soekarno Putri, Indira Gandhi, Benazir Bhitto, atau Qorry Aquino yang sulit sekali dilepaskan dari sosok ayah atau suaminya. Posisi politik kuat yang dimiliki para laki-laki itu dianggap merupakan faktor utama, atau bahkan satu-satunya, yang membuat para perempuan ini maju sebagai pemimpin.
Baca juga:Perempuan sebagai ‘Vote-Getters’: Kompetensi, Popularitas, atau Politik Dinasti?
Di luar institusi partai atau birokrasi, perempuan masih harus berhadapan dengan perwujudan budaya patriarkal mulai dari lingkup terkecil di masyarakat, yakni keluarga.
Selain mengontrol gerak perempuan di ranah publik, laki-laki dalam keluarga kerap mengatur seksualitas dan reproduksi perempuan. Hal ini lantas berimplikasi pada peran sebagai istri atau ibu yang melekat erat pada perempuan dan mempengaruhi performanya dalam karier.
Bukan hal mudah bagi perempuan untuk menentang peran domestik yang disematkan kepadanya. Pasalnya, nilai patriarki yang memayungi peran tersebut telah lama ditanamkan dalam keluarga melalui hierarki dan menyebar luas dalam masyarakat. Interpretasi agama yang bersifat patriarkal semakin menguatkan hal tersebut. Laki-laki sering dianggap mutlak sebagai pemimpin dan perempuan dalam keluarga diharuskan untuk mematuhinya.
Lembaga dan sistem hukum juga sebagian besar sangat menguntungkan laki-laki. Banyak penafsiran dalam sistem yurispridensi dan peradilan bernilai patriarki dan tidak memberikan keadilan bagi perempuan. Ini adalah pekerjaan rumah besar dan tidak mudah untuk diubah yang harus dihadapi perempuan dalam parlemen atau birokrasi.
Media massa yang seksis menambah tekanan lain bagi perempuan di dunia politik. Tidak jarang media mengangkat representasi perempuan dalam birokrasi atau parlemen dengan melekatkan sejumlah bias, objektifikasi, atau stereotip tertentu yang menyudutkan perempuan. Alih-alih memberi perhatian lebih pada kapasitas pemimpin perempuan, sejumlah media justru mencari sisi negatifnya dan memperkuat anggapan perempuan lebih inferior dalam dunia politik dan birokrasi.
Perkara modal politik, sosial, dan ekonomi
Untuk bisa melaju dalam kontestasi politik, perempuan harus memiliki beragam modal. Yang pertama adalah modal politik, yakni pendidikan politik yang mumpuni sebagai bekal perempuan untuk mengatur strategi pemenangan dalam pemilu dan kampanye. Tidak hanya itu, modal politik juga berkaitan dengan penguasaan berbagai isu, keterampilan berorasi, memahami etika politik dan situasi dalam partai politik (internal maupun eksternal), serta pemahaman yang baik mengenai demokrasi.
Berikutnya adalah modal ekonomi, yaitu sumber daya finansial. Hal ini diperlukan untuk pembiayaan kampanye, termasuk biaya menyewa jasa konsultasi ahli politik, mobilisasi massa dan organisasi masyarakat, serta biaya untuk diprioritaskan dalam partai. Tidak seperti laki-laki yang cenderung memiliki finansial lebih kuat karena sudah sejak dulu diarahkan menjadi pencari nafkah utama, perempuan harus bekerja ekstra untuk memenuhi kebutuhan finansial untuk melaju dalam karier politiknya.
Modal terakhir adalah modal sosial, yakni kekuatan berinteraksi yang dapat membawa seseorang menuju proses negosiasi dan memperoleh dukungan baik dari individu maupun kolektif. Dukungan kolektif atau basis massa ini punya andil besar dalam aspek daya tarung politik dan posisi tawar perempuan ketika menjabat sebagai pengambil kebijakan publik.